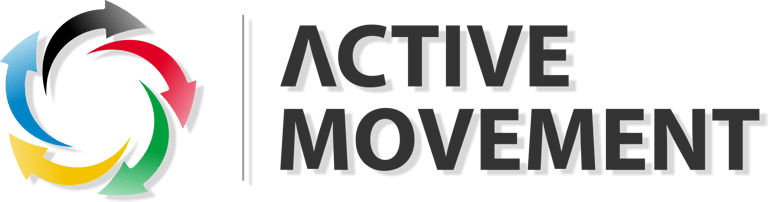Sportswashing: Komplikasi dan Korupsi
ULASAN
N.R. Fadhli
9/29/20257 min read


Gambar: Active Movement Indonesia
Semester ini saya diberi amanah yang agak unik: Dosen Pendidikan Kepelatihan Olahraga yang biasanya sibuk dengan statistik servis bola voli dan program latihan fisik, tiba-tiba harus mengampu mata kuliah filsafat. Bayangkan, dari biasanya menjelaskan biomekanika gerakan lengan saat service, kini harus bicara tentang Heidegger dan tubuh sebagai “ada-di-dunia”. Seusai perkuliahan, saya dan tim dosen yang mengajar bersama yang merupakan dosen kajian sejarah lingkungan duduk bersama sambil menikmati kopi yang kurang original dikantin kampus yang semakin kapital. Kami berdiskusi bukan sedang menilai teknik smash mahasiswa, melainkan mengamati performa analitik mereka saat mengajar selama 4 SKS tadi. Diskusi kami penuh rasa getir tapi juga geli: mahasiswa ternyata lebih cepat memahami logika formasi 4-3-3 ala Ruben Amorim dibanding logika silogisme Aristotelian. Dari situ, kami sepakat minggu depan harus ada materi yang lebih “membumi”, sesuatu yang menyatukan analisis kritis dengan realitas sehari-hari. Mahasiswa harus mampu menjiwai dari lubuk hati materi yang kita sampaikan. Jadilah topik “politik dan olahraga” muncul di meja, dan kami mulai berburu referensi.
Pencarian itu akhirnya membawa kami pada artikel Sportswashing: Complicity and Corruption karya Fruh, Archer, & Wojtowicz (2023). Partner ngajar dari Fakultas Ilmu Sosial (yang sehari-hari meneliti sejarah lingkungan) langsung berseru, “Wah, ini apik iki lek! Persis yang kita lihat di Indonesia!” Saya hanya bisa tertawa dengan nyengir. Bayangkan, dari diskusi tentang bagaimana mahasiswa masih bingung membedakan ontologi dan epistemologi, ujung-ujungnya kami malah menemukan betapa stadion dan turnamen bisa jadi laboratorium politik yang jauh lebih riil daripada kelas filsafat. Di sinilah satirnya: kita ingin mengajarkan filsafat pada mahasiswa olahraga, tetapi justru olahraga itu sendiri, aktivitas mereka sendirilah yang memberi kuliah filsafat terselubung—tentang kekuasaan, pencitraan, dan bagaimana keringat atlet (mereka mahasiswa PKO) bisa jadi esense politik bagi penguasa.
Dalam tulisannya, Fruh langsung menyoroti ketika FIFA menunjuk Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022, dunia terbelah. Sebagian publik terpesona dengan stadion megah dan pesta sepak bola paling akbar di bumi, tetapi sebagian lain menyoroti sisi gelap di balik panggung itu. Ribuan pekerja migran dilaporkan meninggal dunia dalam pembangunan infrastruktur (Pattisson et al., 2021). Sementara isu kebebasan sipil, hak perempuan, dan kelompok minoritas seksual di negara tersebut menjadi sorotan tajam. Banyak pihak lalu menyebut ini sebagai contoh nyata sportswashing—fenomena ketika olahraga diperalat untuk menutupi noda politik dan moral suatu rezim (Fruh et al., 2023).
Ternyata sportswashing sendiri bukan hal baru. Sejak Olimpiade 1936 di Berlin yang dijadikan panggung propaganda Nazi, hingga Piala Dunia 1978 di Argentina di bawah bayang kediktatoran militer (Wilson, 2016). Olahraga telah lama digunakan untuk mempercantik wajah penguasa. Namun dalam era globalisasi, televisi satelit, dan media sosial, dampaknya semakin luas. Olahraga kini bukan hanya hiburan, melainkan bahasa universal yang bisa menyentuh miliaran orang sekaligus. Maka tak heran jika negara, korporasi, atau individu yang memeiliki duit tetapi memiliki catatan buruk berbondong-bondong memakai olahraga sebagai sabun pencuci dosa publik.
Jika kita telisik lebih jauh, sportswashing bekerja dengan cara yang sangat halus. Pertama, ia mengalihkan perhatian publik dari masalah besar. Ketika halaman depan koran dipenuhi dengan berita tentang Lionel Messi yang bersinar di Paris Saint-Germain (klub milik Qatar) maka berita soal pekerja migran yang tereksploitasi di Doha tenggelam ke pojok belakang (Brannagan & Giulianotti, 2018). Kedua, sportswashing mengecilkan skala masalah. Isu pelanggaran HAM dipandang sekadar gangguan kecil, tak sebanding dengan kemegahan turnamen. Ketiga, yang lebih berbahaya, ia menormalisasi pelanggaran. Perlahan-lahan, publik tidak lagi melihat pelanggaran itu sebagai masalah, karena rasa kagum terhadap gemerlap olahraga menempel kuat pada rezim atau korporasi yang ingin membersihkan namanya.
Sportswashing tidak hanya menipu mata publik, tetapi juga menyeret jutaan orang ke dalam lingkaran keterlibatan tanpa sadar. Fans yang membeli tiket, jersey, atau sekadar menonton lewat televisi ikut memperkuat legitimasi pemilik klub yang punya catatan buruk. Pelatih dan atlet yang memilih diam dengan alasan “fokus pada sepak bola” sebenarnya sedang membantu memisahkan klub dari dosa pemiliknya (News.com.au, 2022). Media yang hanya menyoroti skor dan drama di lapangan pun ikut berperan dalam melanggengkan pencitraan. Akhirnya, kita semua, sebagai bagian dari ekosistem olahraga, berada di posisi rawan menjadi bagian dari praktik cuci dosa ini.
Keterlibatan inilah yang disebut complicity. Ia bukan keterlibatan langsung dalam pelanggaran HAM, tetapi keterlibatan tidak langsung yang justru membuat pelanggaran itu bisa terus berlangsung. Contohnya sederhana. Fans Chelsea pernah meneriakkan nama Roman Abramovich, pemilik klub sekaligus oligarki Rusia yang dekat dengan Vladimir Putin, di tengah aksi solidaritas untuk Ukraina (Descalsota, 2022). Teriakan itu tampak sepele, tetapi sesungguhnya menjadi bentuk pembelaan terhadap sosok yang terkait erat dengan rezim penyerang. Hal serupa juga bisa terjadi di Indonesia ketika klub sepak bola lokal dipakai sebagai kendaraan politik. Dukungan fanatik suporter bisa membuat publik lupa bahwa di balik sorak-sorai, ada persoalan transparansi dana atau janji politik yang belum ditepati.
Namun sportswashing tidak berhenti pada masalah keterlibatan saja. Ia juga mencemari nilai luhur olahraga. Klub, turnamen, dan simbol olahraga yang seharusnya menjadi warisan budaya dan sumber identitas komunitas, berubah menjadi alat pencitraan. (Edgar, 2021) menyebut klub dan institusi olahraga sebagai sesuatu yang “sakral”, karena ikatan emosionalnya dengan komunitas, bahkan lintas generasi. Fans yang mengikuti klub selama puluhan tahun demi cinta pada tradisi dan komunitas, tiba-tiba menemukan diri mereka menjadi bagian dari kampanye politik pemilik baru. Nilai kebersamaan dan loyalitas berubah menjadi sekadar kendaraan citra.
Kisah seorang fans Newcastle memberi gambaran dilema ini. Meski sadar klubnya kini dimiliki rezim Saudi dengan catatan HAM kelam, ia tetap mendukung karena klub itu bagian dari kenangan keluarga, ayah, ibu, bahkan identitas kampung halamannya (Rushden, 2021). Di Indonesia, situasi ini terasa dekat dengan klub-klub tradisional seperti Persebaya, Arema, Persib, atau PSMS. Bagi banyak orang, dukungan pada klub bukan hanya soal pertandingan, tetapi bagian dari hidup, bahkan warisan turun-temurun. Jika klub-klub ini dipakai untuk kepentingan sempit politik atau bisnis, maka yang tercemar bukan hanya nama klub, melainkan juga memori kolektif yang diwariskan lintas generasi.
Dari sinilah muncul pertanyaan penting: bagaimana kita melawan sportswashing? Ada dua jalur besar yang bisa ditempuh, meski keduanya sama-sama berat. Pertama adalah dengan menghentikan partisipasi. Fans bisa memboikot pertandingan, sponsor bisa mencabut dukungan, pemain atau pelatih bisa menolak tampil. Kasus di Skotlandia memberi contoh nyata. Raith Rovers memutus kontrak seorang pemain yang terbukti melakukan pemerkosaan setelah protes keras datang dari fans, sponsor, dan pemain lain (Brooks, 2022). Tekanan kolektif itu berhasil, tetapi biayanya tidak kecil. Fans harus meninggalkan klub yang mereka cintai, sponsor harus kehilangan eksposur, dan pemain mempertaruhkan kariernya.
Namun jalur kedua muncul: bukan berhenti, tetapi mengubah cara berpartisipasi. Inilah yang disebut transformasi partisipasi. Sejarah mencatat beberapa contoh luar biasa. Pada Olimpiade 1968, dua sprinter Amerika, Tommie Smith dan John Carlos, mengangkat tangan dengan sarung tangan hitam di podium sebagai simbol perlawanan terhadap rasisme (Tower, 2018). Mereka tidak mundur dari lomba, tetapi mengubah panggung kemenangan menjadi panggung protes. Contoh lebih baru datang dari tim nasional Norwegia yang mengenakan kaos bertuliskan “Human Rights—On and off the pitch” saat kualifikasi Piala Dunia 2022 (Skysports, 2021). Pesan sederhana itu mengingatkan dunia bahwa di balik euforia ada manusia yang haknya terampas.
Di ujung diskusi kami di warung kopi sederhana itu, setelah gelas kopi hitam tinggal ampas, pembicaraan melebar dari filsafat ke kenyataan di sekitar kita. Teman saya yang dosen sejarah lingkungan tersenyum miris, “Lihat saja di Indonesia, praktik seperti ini juga ada, hanya skalanya berbeda”. Kami pun mengangguk.
Kita sering mengira praktik pencitraan lewat olahraga hanya terjadi di level dunia, misalnya Qatar dengan Piala Dunia. Padahal, di dalam negeri, wajah yang mirip juga ada, hanya bentuknya lebih lokal. Pesta olahraga besar seperti Pekan Olahraga Nasional (PON) atau SEA Games sering jadi ajang kebanggaan. Tapi di balik meriahnya seremoni, ada cerita lain: pemborosan anggaran, pembangunan venue yang mangkrak, atau biaya yang membengkak jauh di atas rencana. Contohnya PON Papua 2021, di mana stadion megah memang jadi kebanggaan (Setkab.go.id, 2021), tapi ada cerita miris dibalik kemegahan itu, orang yang diabadikan jadi nama stadion menjadi cosplay rompi KPK (Liputan6.com, 2023). sementara fasilitas dasar masyarakat sekitar masih banyak yang kekurangan. Euforia peresmian seolah menutupi masalah itu.
Hal serupa juga terlihat dalam sepak bola lokal. Klub Liga 1 bukan hanya tim olahraga, tapi juga jadi kendaraan politik. Ada pemilik atau pejabat yang memakai klub untuk menaikkan popularitas menjelang pemilu. Jika tim menang, dianggap sebagai prestasi sang pemilik. Tapi di balik itu, masalah klasik seperti keterlambatan gaji pemain masih sering terjadi, bahkan di level profesional (PanditFootball, 2025). Jadi, kemenangan di lapangan sering dijadikan alat politik, sementara kesejahteraan pemain yang sebenarnya berjuang malah kerap diabaikan.
Yang paling menyedihkan tentu tragedi Kanjuruhan 2022. Ratusan suporter meninggal dunia karena salah kelola pertandingan dan keamanan. Gas air mata ditembakkan ke arah tribun, pintu stadion sulit dibuka, dan manajemen krisis sangat buruk. Semua itu menunjukkan betapa nyawa manusia bisa dikorbankan demi “kompetisi tetap berjalan”. Bukan hanya soal teknis, tapi cara olahraga diposisikan: lebih penting menjaga citra pertandingan, meski mengabaikan keselamatan penontonnya (Agustin et al., 2025).
Obrolan kami sore itu dari membahas filsafat di kelas, berlanjut ke politik global lewat artikel Sportswashing: Complicity and Corruption, lalu kembali ke tanah air yang penuh cerita serupa. Rasanya ironis, tapi juga nyata—bahwa olahraga yang seharusnya jadi ruang kebersamaan dan nilai luhur sering direduksi menjadi panggung pencitraan. Dari warung kopi itu kami pulang naik honda win reot (motor kami sama) dengan kesadaran sederhana: menjaga kemurnian olahraga dari kepentingan politik dan bisnis bukan hanya urusan negara atau federasi, tapi juga tugas moral dan sosial semua penggiat olahraga. Kalau tidak, sorak-sorai di stadion akan terus menjadi musik pengiring bagi mereka yang sedang mencuci tangan dari noda sejarah.
Daftar Rujukan
Agustin, E. A. T., Mumtaz, K. K., Mapandiy, V. D., Zulfariza, A. A., Pakpahan, F. N., Rahman, N. A., & Putri, A. R. N. (2025). Pelanggaran Ham Dalam Tragedi Kanjuruhan 2022: Perspektif Keadilan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. Media Hukum Indonesia (MHI), 3(3).
Brannagan, P. M., & Giulianotti, R. (2018). The soft power–soft disempowerment nexus: the case of Qatar. International Affairs, 94(5), 1139–1157.
Brooks. (2022). Raith Rovers women’s captain resigns amid fury over David Goodwillie signing. https://www.theguardian.com/football/2022/feb/01/raith-rovers-womens-captain-resigns-amid-fury-over-david-goodwillie-signing
Descalsota, M. (2022). Chelsea fans chanted Russian oligarch and owner Roman Abramovich’s name during a soccer game, interrupting applause for Ukraine. Insider.
Edgar, A. (2021). Super leagues and sacred sites. In Sport, Ethics and Philosophy (Vol. 15, Issue 3, pp. 305–307). Taylor & Francis.
Fruh, K., Archer, A., & Wojtowicz, J. (2023). Sportswashing: Complicity and corruption. Sport, Ethics and Philosophy, 17(1), 101–118.
Liputan6.com. (2023). KPK Telisik Potensi Korupsi Stadion Lukas Enembe dalam Anggaran Dana PON XX Papua 2021. https://www.liputan6.com/news/read/5370686/kpk-telisik-potensi-korupsi-stadion-lukas-enembe-dalam-anggaran-dana-pon-xx-papua-2021
News.com.au. (2022). Coach squirms amid questions about Saudi Arabia executing 81 people in one day. https://www.news.com.au/sport/football/coach-squirms-amid-questions-about-saudi-arabia-executing-81-people-in-one-day/news-story/81512fcf3e6fef564711fa008d75c3cf
PanditFootball. (2025). Penunggakan Gaji Sebagai Gejala Kronis Sepakbola Indonesia. https://panditfootball.com/pandit-sharing/215541/PFB/250515/penunggakan-gaji-sebagai-gejala-kronis-sepakbola-indonesia
Pattisson, P., McIntyre, N., Mukhtar, I., & Eapen, N. (2021). Revealed: 6,500 migrant workers have died in Qatar since World Cup awarded. The Guardian, 23.
Rushden, M. (2021). Guardian Football Weekly Podcast.
Setkab.go.id. (2021). Buka PON XX, Presiden: Pekan Olahraga Nasional Pertama di Tanah Papua. https://setkab.go.id/buka-pon-xx-presiden-pekan-olahraga-nasional-pertama-di-tanah-papua/
Skysports. (2021). Qatar 2022 World Cup: Norway players protest to express concerns over hosts’ human rights record. https://www.skysports.com/football/news/11095/12255827/qatar-2022-world-cup-norway-players-protest-to-express-concerns-over-hosts-human-rights-record
Tower, N. (2018). Olympic project for human rights lit the fire for 1968 protests. Global Sport Matters.
Wilson, J. (2016). Angels with dirty faces: how Argentinian soccer defined a nation and changed the game forever. Bold Type Books.
Baca Juga Lainnya: Artikel
OUR ADDRESS
Perum Pondok Bestari Indah, Blk. B1 No.49B, Dusun Klandungan, Landungsari, Kec. Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65151
CONTACT US
WORKING HOURS
Monday - Friday
9:00 - 18:00