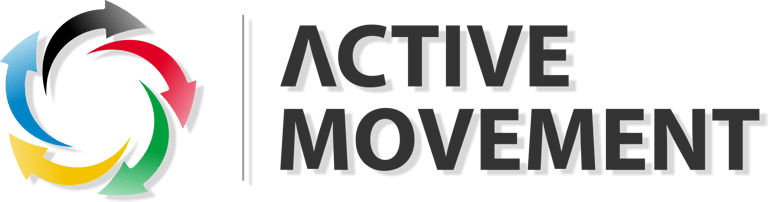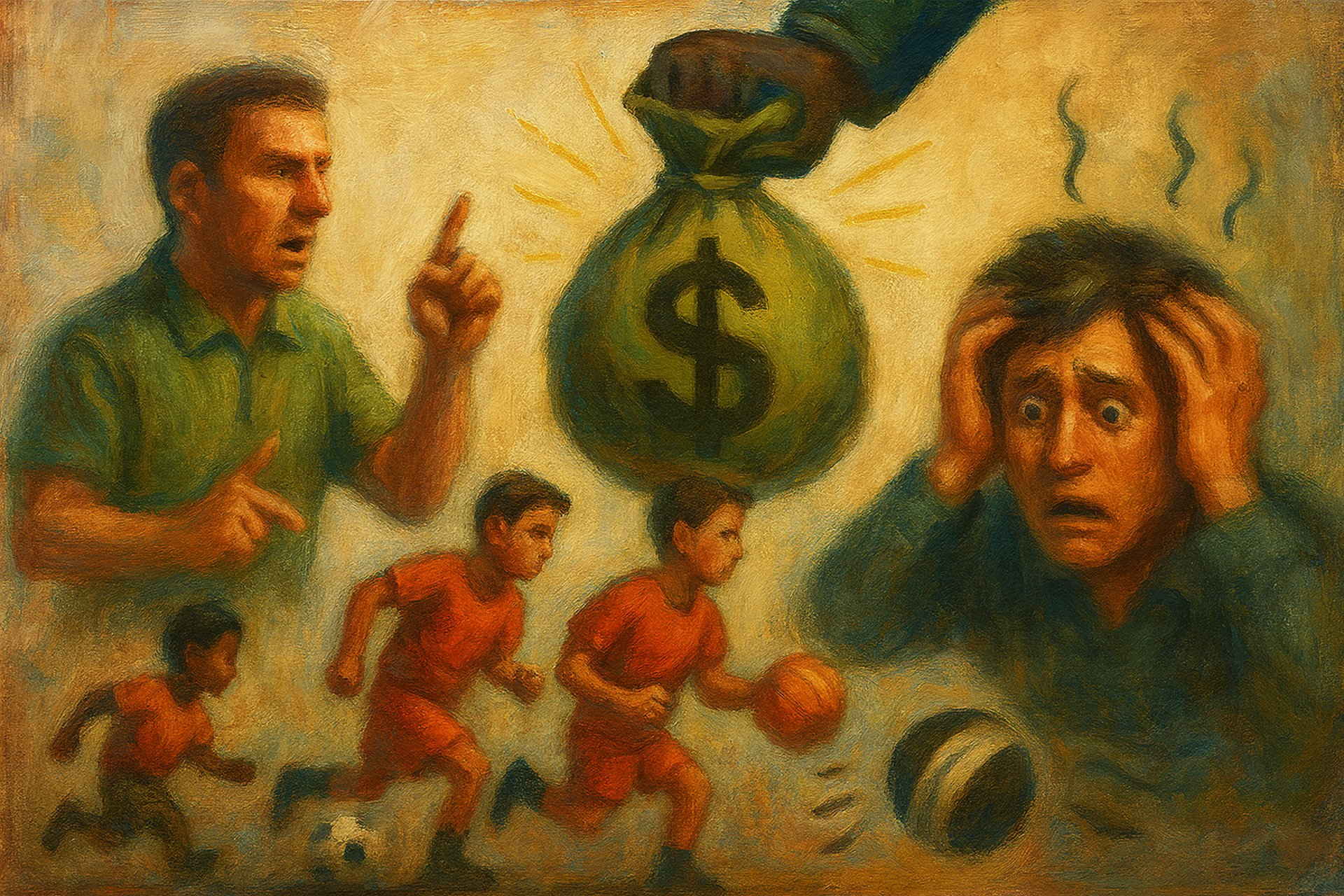
Pedagogi Kritis, Neoliberalisme, dan Kegelisahan dalam Pendidikan Jasmani
OPINI
D.S. Yudasmara
9/25/20254 min read
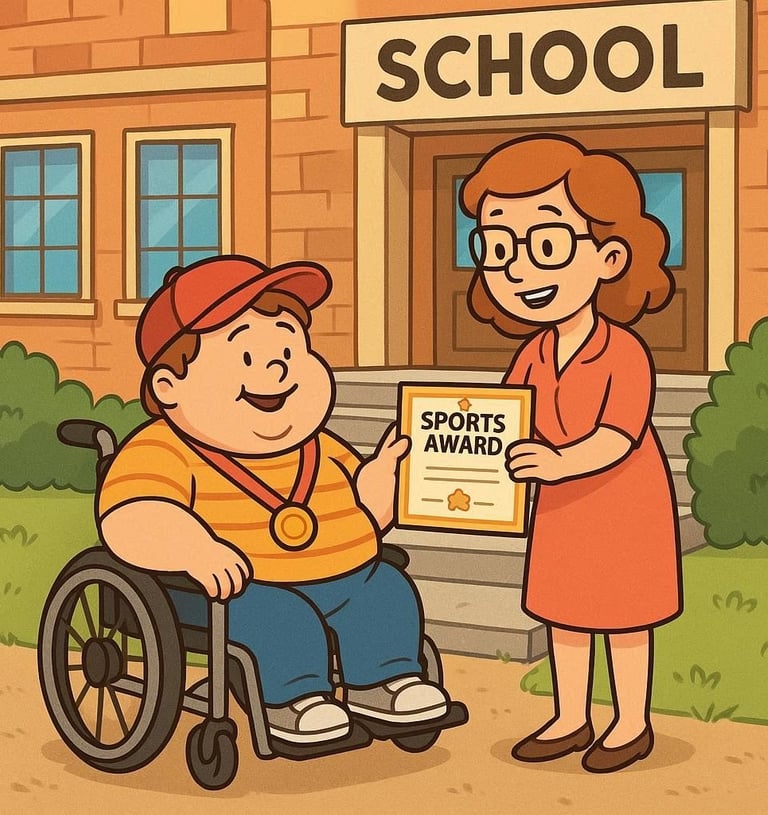
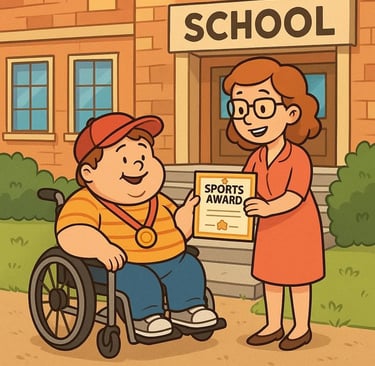
Gambar: Active Movement Indonesia
Dalam wacana pendidikan jasmani kontemporer, istilah transformasional kerap digunakan untuk menandai arah baru pengajaran yang tidak hanya berorientasi pada keterampilan fisik, tetapi juga pada perubahan sosial. Namun, persoalan muncul ketika istilah ini dipakai terlalu longgar, hingga mengaburkan perbedaan antara transformasi yang sejati dan perubahan kosmetik semata. Kegelisahan inilah yang ditangkap oleh Tinning dalam subjudulnya “Disquiet in the tent”, yang menegaskan perlunya kriteria yang jelas untuk menilai apakah suatu praktik pembelajaran dan pendidikan benar-benar mengubah kesadaran dan pemahaman siswa tentang diri, tubuh, dan kehidupan mereka di masyarakat, atau sekadar variasi metode mengajar yang tidak menyentuh akar persoalan serta tidak memiliki kebermaknaan apapun dalam hidup mereka.
Dalam chapternya, Tinning menuliskan kutipan menarik dari McLaren (1998) yang menyoroti bagaimana pedagogi kritis postmodern dengan penekanannya pada nilai-nilai diversity (keberagaman) dan inclusion (inklusivitas) rentan dikooptasi oleh neoliberalisme. Ia menyatakan bahwa karena “postmodern critical pedagogy has an emphasis on values such as diversity and inclusion, its language is easily co-opted by neo-liberalism and has become an ally of new capitalism and neo-liberal educational policy.” Sebuah ungkapan tentang nilai-nilai yang tampak radikal dan revolusioner yang bertujuan untuk upaya penggugatan terhadap diskriminasi, namun akhirnya hanya menjadi jargon yang kosong yang nyatanya dibalik itu hanya dipergunakan untuk kepentingan branding dan legitimasi terhadap kebijakan-kebijakan yang “menindas” yang sejatinya mengarahkan kepada neoliberalisme itu sendiri.
Universitas, misalnya, kerap menggunakan istilah “inklusif” atau “beragam” untuk memasarkan program kelas internasional dengan biaya tinggi, yang justru menyingkirkan kelompok marjinal. Perusahaan mengusung kampanye keberagaman demi citra progresif, tetapi tetap melanggengkan praktik rekrutmen yang bias kelas. Sekolah menyebut dirinya ramah inklusi, namun tidak menyediakan fasilitas adaptif yang nyata bagi siswa difabel. Dengan demikian, “diversity” dan “equity” dalam tangan neoliberalisme bergeser makna: dari alat perjuangan sosial menjadi alat pencitraan. Alih-alih membongkar struktur ketidakadilan, istilah ini dipakai untuk mempertahankan status quo yaitu pola lama yang bias kelas, gender, maupun tubuh yang terus dilanggengkan tanpa digugat.
Kecenderungan mempertahankan status quo juga tampak pada praktik guru pendidikan jasmani. Mengacu pada Giddens (1991), banyak guru lebih dekat pada orientasi life politics ketimbang emancipatory politics. Giddens mendefinisikan life politics sebagai “a politics of choice” yang berpusat pada pilihan gaya hidup dan identitas personal, bukan pada upaya membebaskan diri dari kondisi yang menindas. Praktiknya, guru lebih peduli pada siswa berbakat, menekankan standar tubuh ideal, atau sekadar memperkaya variasi olahraga tanpa menyentuh isu sosial.
Sebaliknya, politik emansipatori menuntut keterlibatan pendidikan jasmani dalam menghilangkan diskriminasi dan membuka ruang kesetaraan. Guru yang memiliki pemahaman ini memberi kesempatan setara bagi semua siswa, melawan stereotip gender dalam olahraga, serta memodifikasi alat atau aturan agar siswa dengan disabilitas bisa berpartisipasi penuh. Dengan pendekatan ini, pendidikan jasmani menjadi arena pemberdayaan, bukan sekadar ajang reproduksi norma dominan.
Kegelisahan Tinning terkait istilah transformasional bermula dari berbagai kenyataan bahwa banyak praktik pedagogi hanya berhenti pada level “kosmetik” atau tampak pada permukaan yang terlihat sangat manis karena polesan meskipun di dalamnya mungkin saja ada kejelekan yang coba disembunyikan oleh polesan tersebut. Tinning dalam chapternya menuliskan bahwa “we need clarity about what counts as evidence of transformation” yang bertujuan agar istilah ini tidak direduksi dan dimaknai menjadi sekadar variasi metode. Misalnya, guru mengganti sepak bola dengan futsal karena keterbatasan sarpras, atau menggunakan aplikasi fitness tracker dalam pembelajaran. Perubahan ini membuat kelas lebih segar, tetapi tidak menyentuh persoalan diskriminasi, relasi kekuasaan, atau bias tubuh.
Transformasi substantif, sebaliknya, adalah ketika guru membawa siswa pada kesadaran kritis. Contohnya, guru membahas stereotip gender dalam olahraga, memberi ruang bagi siswa perempuan untuk menjadi kapten tim, atau menyoroti bagaimana standar tubuh ideal yang seolah-olah menyingkirkan siswa bertubuh gemuk dan tidak memberi ruang kepada siswa yang kebetulan memiliki tubuh yang gemuk. Guru juga bisa menghubungkan olahraga dengan isu akses fasilitas di masyarakat, sehingga siswa tidak hanya belajar teknik dasar dan kemampuan fisik, tetapi juga memahami olahraga sebagai refleksi struktur social kehidupan masyarakat karena sejatinya olahraga juga merupakan “microcosmos” dari kehidupan.
Dua dimensi penting dari transformasi substantif adalah menggugat relasi kuasa dalam kelas serta membongkar bias tubuh, gender, dan norma heteronormatif. Dalam hal relasi kuasa, guru dapat melibatkan siswa dalam merumuskan aturan permainan atau memberi kesempatan kepemimpinan kepada siswa yang biasanya tersisih. Sementara dalam bias tubuh dan gender, guru menolak candaan merendahkan tubuh gemuk, membiarkan siswa memilih olahraga tanpa batasan gender, serta menegaskan bahwa semua pilihan olahraga valid terlepas dari norma heteronormatif. Praktik semacam ini menjadikan pendidikan jasmani bukan sekadar ruang pembentukan fisik, melainkan arena untuk menanamkan kesadaran kritis tentang diri, tubuh, dan masyarakat.
Tulisan ini ingin mencoba menunjukkan bahwa istilah “transformasional” dalam pedagogi terutama Pendidikan Jasmani harus dipahami secara hati-hati. Transformasi yang dikatakan sejati bukan sekadar variasi metode pembelajaran, tetapi keberanian mengubah cara siswa pandang siswa terhadap tubuh, identitas, dan ketidakadilan sosial. Ketika wacana sosial seperti diversity dan equity dikooptasi oleh neoliberalisme, pendidikan jasmani berisiko kehilangan daya kritisnya. Karena itu, penting bagi guru untuk keluar dari jebakan yang disebut sebagai “politik kehidupan” yang memperkuat status quo (fenomena yang selama ini mengakar kuat dan dominan dalam pemahaman pelakunya), dan bergerak menuju “politik emansipatori” yang menantang diskriminasi serta membuka ruang bagi perubahan sosial yang lebih adil.
Dalam konteks Indonesia, persoalan kooptasi wacana sosial oleh neoliberalisme juga terlihat nyata. Istilah “inklusi” kerap digunakan dalam dokumen kurikulum dan kebijakan pendidikan, namun implementasinya masih minim. Banyak sekolah mengklaim ramah difabel atau berperspektif gender, tetapi fasilitas olahraga masih tidak aksesibel, guru belum mendapat pelatihan inklusif, dan siswa perempuan kerap dipinggirkan dalam kegiatan fisik. Di sisi lain, pendidikan jasmani seringkali lebih menekankan pada pencapaian prestasi olahraga tertentu sebagai kebanggaan institusi sebuah bentuk branding daripada mengupayakan pemerataan akses dan kesetaraan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan jasmani di Indonesia masih cenderung beroperasi dalam kerangka politik kehidupan, sementara agenda politik emansipatori yang menantang ketidakadilan sosial dalam tubuh, gender, dan akses fisik seharusnya masih menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar bagi guru, penyusun kurikulum, dan pemangku kebijakan. Namun jika elemen-elemen tersebut sekali lagi terjebak pada narasi politik kehidupan tersebut maka, relasi kuasa dan penindasan tidak akan pernah hilang selamanya dari praktik pedagogi kita. Paolo Freire dalam bukunya “The Pedagogy of Oppresed” dengan terang menyebutkan bahwa dalam Praktik pedagogi khususnya dalam Penjas sangat rentan melahirkan penindas-penindas baru, guru-guru yang elitis, seksis serta konservatif yang berkedok pada jargon perubahan, karena praktiknya yang benar-benar tidak dipahami sebagai Praktik pembebasan.
OUR ADDRESS
Perum Pondok Bestari Indah, Blk. B1 No.49B, Dusun Klandungan, Landungsari, Kec. Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65151
CONTACT US
WORKING HOURS
Monday - Friday
9:00 - 18:00