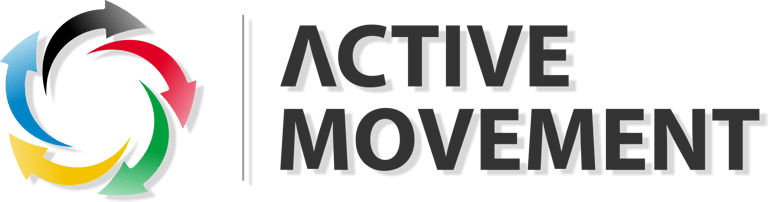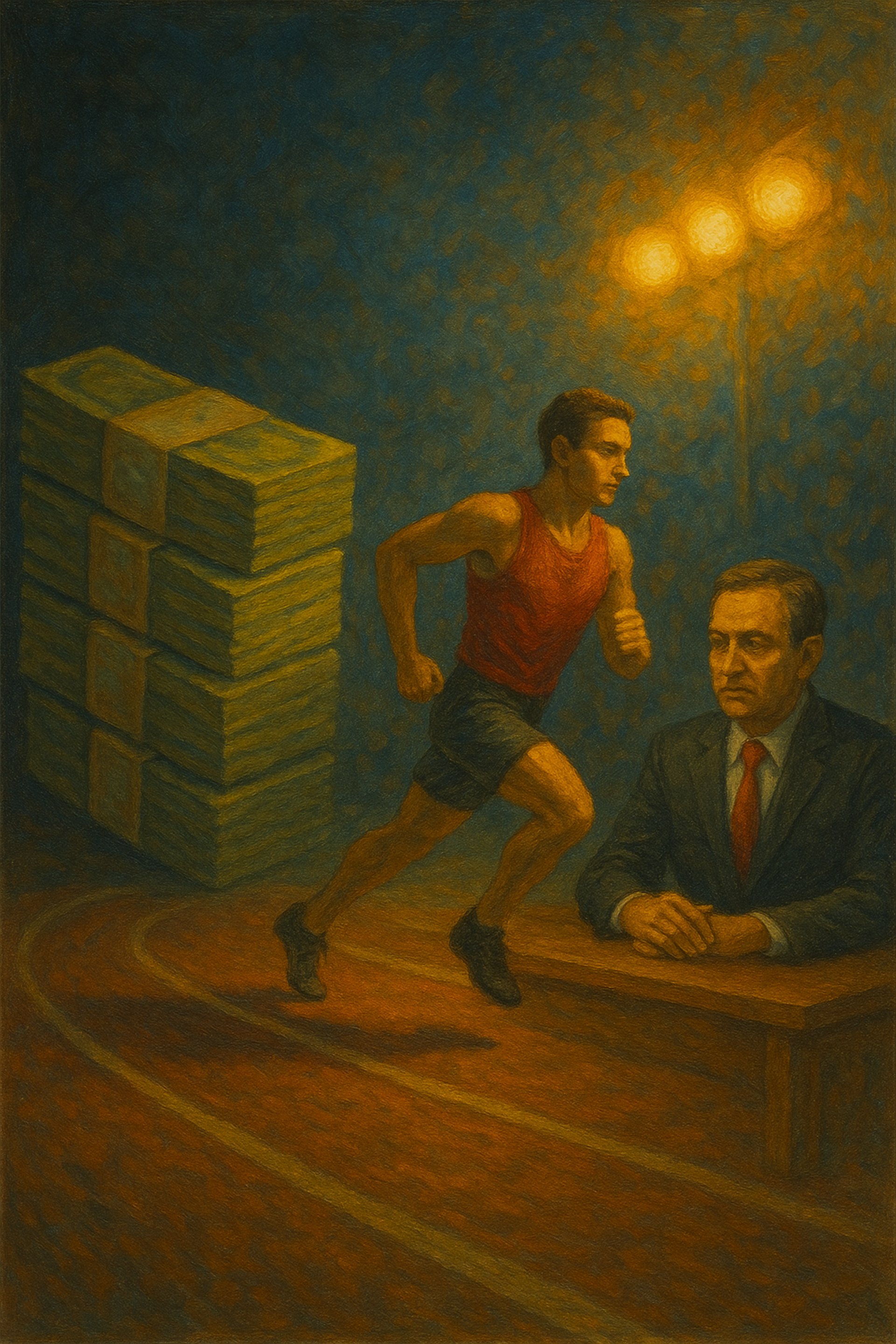
Mengapa Negara Mau Menghabiskan Triliunan Rupiah untuk Event Olahraga?
ESAI NARATIF
N.R. Fadhli
9/28/20254 min read
Gambar: Active Movement Indonesia
Saya masih ingat hari itu, ketika pesawat yang saya tumpangi mendarat sangat lembut di Bandara Internasional Lombok-Praya atau yang sekarang memiliki nama Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, Lombok. Udara panas menyambut dari balik jendela, bercampur dengan aroma asin laut yang terbawa angin, serasa sudah merasakan dentuman musik party di Gili Trawangan. Perjalanan penelitian yang panjang menanti, tapi langkah saya terhenti ketika melihat sosok yang tak asing di area parkir bandara. Ia adalah teman lama dari masa kuliah S2, Batak tulen dengan suara lantang khas yang selalu terdengar setengah berteriak seperti orang menantang berantem, meski maksudnya hanya mengobrol biasa. Kami sama-sama terkejut sekaligus gembira, lalu tanpa pikir panjang memutuskan singgah di sebuah kedai kopi sederhana dekat bandara sebelum melanjutkan perjalanan masing-masing.
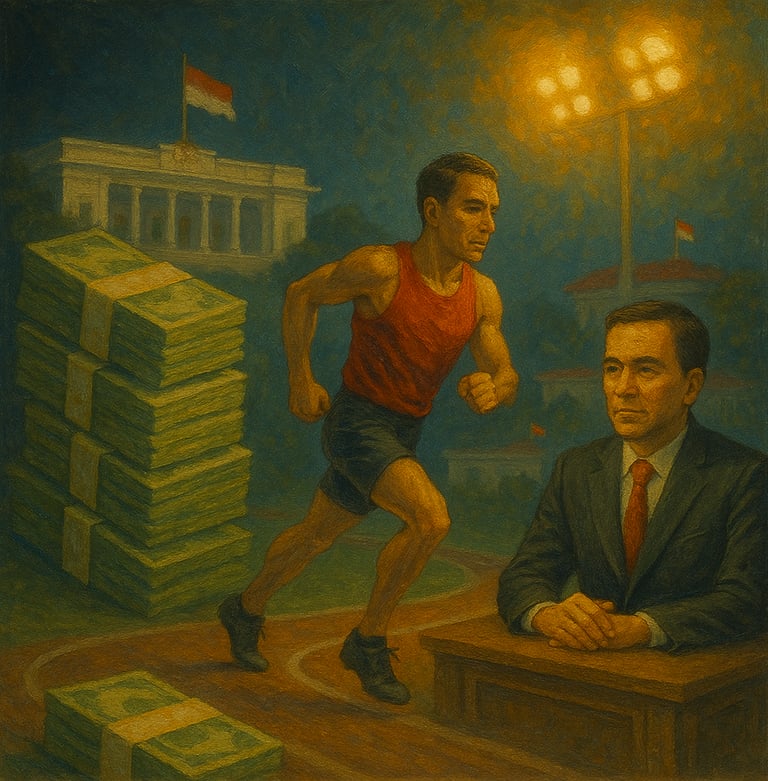
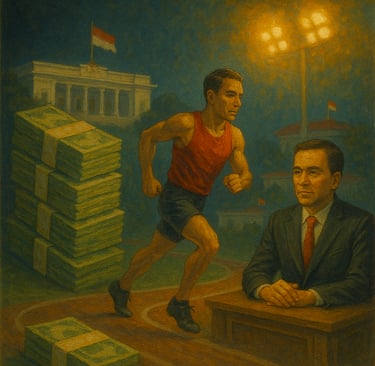
Di meja kayu yang masih berbau pernis baru, kami menyeruput kopi hitam panas sembari melepas rindu. Obrolan awalnya mengalir ringan: kabar keluarga, cerita pekerjaan, sampai gosip kawan lama yang kini menikah untuk ketiga kalinya. Suaranya tetap keras, membuat beberapa pengunjung lain menoleh, tapi itulah dirinya, tak pernah bisa setengah-setengah ketika bicara.
Sampai akhirnya, percakapan kami berbelok. Saya tiba-tiba bertanya, “Eh, dulu kau sempat pulang nggak waktu PON di Medan?” Ia terdiam sejenak, menatap ke luar jendela, lalu meneguk kopinya dengan pelan. Dengan nada penuh tenaga, ia menjawab, “Pulanglah, bah. Masa PON di kampung sendiri nggak pulang? Tapi jujur aja, banyak stadion waktu itu nggak beres. Katanya sudah habis ratusan miliar, tapi hasilnya… ya gitu. Entah di mana uangnya.”
Saya hanya bisa mengangguk. Terbayang stadion setengah jadi, rumput lapangan tak terawat, dan cat dinding yang mulai mengelupas meski baru selesai dicat. Rasanya ironis. Saya tersenyum miris lalu menimpali, “Jangan-jangan di negeri kita ini, yang paling cepat berlari bukan atlet, tapi anggaran.” Ia tertawa keras, tawanya menggelegar sampai orang di meja sebelah ikut menoleh. Namun di balik tawa itu, saya tahu ada getir yang kami bagi bersama. Apalagi kita sama-sama mengaku sebagai sport scientis.
Obrolan di kedai kopi itu tiba-tiba mengingatkan saya pada berita lain. Pemerintah pusat telah mengucurkan Rp. 811 miliar untuk pembangunan dan renovasi 18 venue PON Aceh–Sumut, tapi publik justru disuguhi kabar carut-marut persiapan (VOA Indonesia, 2024). Lalu saya teringat Qatar, yang rela menghabiskan USD 220 miliar atau sekitar Rp 3.344 triliun demi menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 itu merupakan angka fantastis yang menjadikannya Piala Dunia termahal sepanjang sejarah (CNBC Indonesia, 2022). Sebagai perbandingan, Indonesia sendiri merencanakan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp 466 triliun, meskipun tidak semuanya berasal dari APBN (IKN.go.id, 2023).
Jika dipikir-pikir dengan lebih lambat dan renungan yang dalam, angka-angka itu menggelitik sekaligus mengejutkan. Bayangkan, sebuah event olahraga yang hanya berlangsung tidak lebih dari sebulan bisa menelan biaya lebih besar daripada membangun sebuah kota baru yang dirancang untuk menampung generasi tik-tok masa depan. Lalu pertanyaan pun muncul: apa sebenarnya yang dikejar negara ketika menggelontorkan dana sebesar itu hanya demi sebuah event olahraga?.
Paling baru, berita tentang kesiapan Indonesia dalam Sea Games yang tinggal hitungan hari, anggran hanya cukup untuk 120 atlet. Itu disampaikan menteri pemuda olahraga yang baru, Eric Tohir. Fenomena ini memperlihatkan paradoks. Negara sering rela menggelontorkan triliunan untuk citra politik lewat event olahraga, tapi ironisnya, untuk kebutuhan mendesak seperti SEA Games yang tinggal dua bulan, perencanaannya justru amburadul. Ini menegaskan bahwa logika symbolic capital ala Bourdieu tidak selalu diimbangi dengan tata kelola anggaran yang rasional dan transparan.
Sejarah memberi kita petunjuk. Sejak Yunani kuno, olahraga sudah menjadi panggung politik. Olimpiade bukan hanya tentang adu fisik, tetapi ritual yang memperlihatkan kejayaan polis. Berabad-abad kemudian, Nazi Jerman menggunakan Olimpiade Berlin 1936 untuk propaganda supremasi bangsa Arya. Stadion megah, parade militer, dan sorotan media diarahkan untuk mencitrakan kekuasaan. Namun, justru di sana, Jesse Owens, seorang atlet kulit hitam dari Amerika meruntuhkan narasi itu dengan empat medali emas-ada filmnya juga itu, sangat inspiratif. Sejak itu kita belajar: olahraga bisa menjadi alat legitimasi, tapi juga bisa menjungkirbalikkan kekuasaan.
Indonesia pun punya cerita sendiri. Tahun 1963, Soekarno meluncurkan GANEFO sebagai tandingan Olimpiade. GANEFO bukan sekadar pertandingan, melainkan simbol perlawanan ideologis terhadap dominasi Barat. Bung Karno tahu, olahraga bisa menjadi bahasa diplomasi yang lebih halus daripada senjata, dan sekaligus sarana untuk menunjukkan kemandirian politik.
Di era sekarang, logikanya tetap sama, meski dengan wajah berbeda. Negara rela menghabiskan triliunan rupiah karena tahu bahwa olahraga adalah modal simbolik. Filsuf asal Prancis, Pierre Bourdieu menyebutnya symbolic capital: pengakuan yang tak kasat mata, tapi berpengaruh besar. Negara yang sukses menggelar event akan dipandang modern, kuat, dan beradab.
Antonio Gramsci menambahkan, “inilah hegemoni”. Stadion megah, seremoni pembukaan, bendera berkibar, dan lagu kebangsaan menciptakan rasa bangga kolektif. Warga merasa terikat dalam identitas nasional, dan rasa ini memperkuat legitimasi politik penguasa tanpa perlu paksaan. Hal menunjukkan bahwa menjadi tuan rumah event olahraga global adalah salah satu cara paling efektif untuk mengubah citra internasional. Qatar adalah contoh jelas: negara kecil di Teluk yang tiba-tiba menjadi pusat perhatian dunia, bukan karena perang, melainkan karena sepak bola.
Sementara itu filsuf berkepala plontos Michel Foucault membawa kita ke lapisan yang lebih halus: tubuh atlet. Baginya, tubuh adalah arena politik. Tubuh yang dilatih, didisiplinkan, dan dipamerkan adalah representasi dari negara yang mengklaim keberhasilan membentuk warganya. Setiap lompatan, setiap sprint, adalah narasi politik tentang siapa yang kuat dan berdaulat.
Namun di balik semua logika itu, ada sisi lain yang tak kalah penting: dilema moral dan kritik publik. PON Aceh–Sumut dengan Rp 811 miliar yang belum menghasilkan fasilitas sempurna adalah satu contoh. Stadion-stadion baru sering berakhir sepi setelah event usai. Infrastruktur terbengkalai, biaya perawatan membengkak, sementara manfaat langsung untuk masyarakat minim. Pertanyaan mendasar pun muncul: pantaskah uang rakyat sebesar itu dialokasikan hanya demi tontonan, sementara sekolah masih reyot dan rumah sakit kekurangan tenaga medis?
Guy Debord pernah menulis tentang society of the spectacle, masyarakat tontonan. Event olahraga global adalah tontonan paling megah abad ini. Negara rela membayar mahal karena tahu dunia sedang menonton. Dalam sekejap, nama bangsa bisa melesat ke panggung global, reputasi bisa dibentuk ulang, citra bisa dipoles. Bahkan beberapa waktu lalau, suporter tarkam voli di pinggiran Pacitan membakar lapangan karena Rivan tidak jadi datang.
Kembali ke kedai kopi di pinggir jalur Bandara-Kota Mataram, suara tawa lantang kawan saya masih terngiang. Ia berkata, “Kalau stadion itu akhirnya jadi, orang mungkin lupa soal anggaran. Yang penting bisa lihat tim kita main”. Saya hanya tersenyum, walau dalam hati bertanya: apakah benar olahraga cukup untuk menutupi segala luka struktural? Atau justru di situlah letak politiknya mengalihkan perhatian kita dengan euforia, sementara hal-hal mendasar tertinggal?
Olahraga memang punya daya magis. Ia bisa menyatukan bangsa, memberi legitimasi penguasa, dan membuka pintu diplomasi. Tapi ia juga bisa menjadi selubung yang menutupi masalah. Itulah mengapa negara rela menghabiskan triliunan rupiah: bukan hanya demi medali, tetapi demi panggung politik, demi citra yang ingin dipamerkan, demi kekuasaan yang ingin diperkuat.
Dan di balik setiap sorak sorai di stadion, ada gema lain yang lebih samar tapi nyata: suara kekuasaan yang sedang memainkan perannya.
Baca Juga Lainnya Disini: Artikel
OUR ADDRESS
Perum Pondok Bestari Indah, Blk. B1 No.49B, Dusun Klandungan, Landungsari, Kec. Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65151
CONTACT US
WORKING HOURS
Monday - Friday
9:00 - 18:00