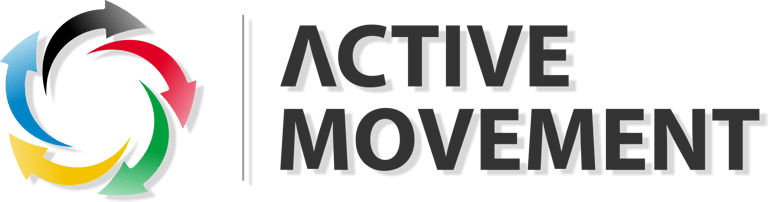Beberapa hari setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan jam tangan mewah merk Rolex (dari kantong pribadi) kepada para pemain Timnas Indonesia sebagai bentuk apresiasi usai lolos babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026, Garuda justru tumbang dengan skor akhir 6-0 dari Jepang. Ini penampilan terburuk sejak kualifikasi piala dunia mungkin dengan catatan dominasi total tim Jepang dengan 71% penguasaan bola, 22 tembakan (10 tepat sasaran), 10 peluang emas, 10 tendangan sudut, serta akurasi umpan 90% (583 dari 645), sementara lawannya tidak menghasilkan satu pun tembakan, peluang, atau tendangan sudut, hanya mencatat 29% penguasaan bola dan akurasi umpan 76% (202 dari 267). Kekalahan ini bukan hanya telak secara angka, tapi juga telanjang secara simbolik, bahwa euforia tak bisa menutupi ketimpangan dalam pembinaan olahraga nasional.
Bukan salah para pemain. Bukan pula semata menjadi tanggung jawab pelatih. Tapi ini saatnya kita menoleh lebih dalam, ada yang salah dalam cara negara memperlakukan olahraga. Apresiasi bombastis ke cabang populer dan perlakuan seadanya ke cabang lain mengungkap wajah asli sistem olahraga kita, penuh ketimpangan, simbolisme, dan pengabaian terhadap esensi pembinaan.
Jika kita meminjam perspektif teori kritis dari Frankfurt School, terutama gagasan Herbert Marcuse dan Theodor Adorno dalam bukunya Bottomore (2019) yang berjudul “Mazhab Frankfurt: Gagasan dan kritik”, dan dalam penelitian Corradetti, C. (2013) olahraga bukan sekadar aktivitas jasmani atau ajang kompetisi. Ia sudah menjadi komoditas budaya—produk yang dikemas, dijual, dan dikonsumsi publik dalam kerangka ekonomi pasar dan kekuasaan politik. Dalam konteks Indonesia hari ini, sepak bola menjelma jadi alat pencitraan, alat legitimasi, bahkan ajang bagi negara menunjukkan "kehadiran".
Maka ketika Timnas lolos dari fase grup Kualifikasi Piala Dunia dan mencetak sejarah, apresiasi yang berlebihan pun mengalir. Pemain diajak berpesta, dipuji di media, dan akhirnya diganjar jam tangan mewah. Namun pada saat yang sama, di sisi yang jauh dari sorotan, para atlet dari cabang olahraga lain justru dipulangkan lewat Zoom, alasannya masih sama, efisiensi anggaran. Seperti yang terungkap dalam laporan BBC Indonesia . Bukan karena mereka tak berprestasi, banyak dari mereka juara Asia bahkan level Dunia, tapi karena mereka bukan “produk yang laku dijual”.
Ini bukan sekadar soal jam tangan atau pelatihan daring. Ini soal bagaimana negara memaknai pembinaan olahraga. Apakah olahraga dipandang sebagai ruang pembentukan karakter, pengembangan sumber daya manusia, dan investasi jangka panjang? Ataukah hanya sebagai panggung populis yang diliputi sorotan media dan euforia sesaat?
Teori kritis menyebut ini sebagai bentuk false consciousness (kesadaran palsu) teori yang awalnya dikembangkan oleh Marx dan Engels untuk menjelaskan tindakan dan perilaku kaum borjuis. Saat ini mungkin bisa dibentuk oleh media dan institusi dominan, yang membuat masyarakat menerima sesuatu yang tidak adil sebagai hal yang wajar. Kita diajak untuk percaya bahwa pemberian Rolex adalah bentuk keberpihakan negara, bahwa sepak bola kita saat ini adalah bentuk kebangkitan nasional, padahal realitas di balik layar menunjukkan struktur yang timpang dan penuh bias terhadap cabang populer.
Bahkan kekalahan telak dari Jepang pun tak sepenuhnya menyadarkan kita bahwa jam mewah bukanlah substitusi dari sistem pembinaan yang sehat. Jepang adalah contoh negara yang membangun sistem olahraga sejak usia dini, dengan basis sekolah, pembinaan berjenjang, dan kompetisi rutin dari level akar rumput. Mereka tidak memberikan simbol-simbol mewah kepada atletnya hanya karena satu kemenangan emosional. Mereka membentuk juara lewat konsistensi, bukan kejutan.
Kita mungkin perlu memaksa untuk jujur mengakui, jika pembinaan olahraga di Indonesia lebih sering digerakkan oleh logika kapitalisme dan pencitraan politik, bukan oleh kebutuhan jangka panjang. Ini terlihat dari pola distribusi anggaran, fasilitas, eksposur media, hingga insentif. Cabang populer seperti sepak bola, bulu tangkis, dan beberapa yang "naik daun", seperti voli putri, cenderung mendapat perhatian dan dukungan besar. Sementara cabang lain yang lebih “sunyi”, seperti kasus saat ini, wushu, panahan, menembak, bahkan atletik, sering kali harus bertahan hidup dengan sumber daya minim, PELATNAS apa adanya, atau bahkan ditinggalkan ketika tidak lagi relevan secara politis.
Padahal, tidak ada cabang olahraga yang inferior. Yang ada hanyalah sistem yang memperlakukan mereka secara tidak setara. Ketika kita mengikuti ajang multi event sebagai contoh Olimpiade, SEA Games atau Asian Games, medali yang didapat sama, satu untuk setiap nomor, bahkan jika dihitung olahraga nomor individu lebih efisien dari sisi anggaran jika dibanding olahraga beregu. Ketika negara memilih untuk menyanjung sebagian dan melupakan yang lain, maka kita sedang menciptakan ekosistem yang timpang dan tidak adil, tempat atlet hanya dihargai jika tampil di layar, bukan karena perjuangannya.
Maka, kekalahan 6-0 dari Jepang bukanlah akhir. Tapi ia bisa jadi titik balik jika kita mau merenung. Apresiasi tetap penting, tapi harus adil dan berbasis prestasi, bukan popularitas. Pelatnas bukan sekadar pengeluaran, tapi investasi yang membentuk mentalitas juara. Dan pembinaan bukan proyek pencitraan, tapi kerja panjang yang butuh keberanian melawan logika pasar.
Negara harus kembali ke esensi dasar, hadir untuk semua atlet, bukan hanya mereka yang viral. Memberikan keadilan dalam pembinaan, bukan hanya hadiah dalam kemenangan. Jika tidak, kita hanya akan terus berputar dalam siklus yang sama, kita terbuai di puncak euforia, lalu kecewa di dasar kenyataan. Karena dalam olahraga, jam tangan boleh mewah. Tapi tanpa sistem yang kuat, kita akan terus kalah baik di lapangan maupun dalam makna.