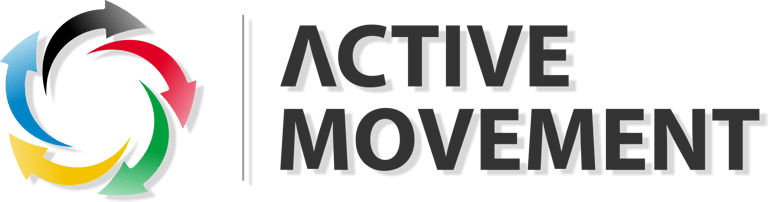Dari Lapangan ke Ruang Kelas: Antara Detak Jantung Digital dan Nurani Pendidikan
ESAI NARATIF
N.R. Fadhli
11/14/20253 min read


Ilustrasi: Active Movement Indonesia
“Anak-anak SD harus mulai belajar coding,” ujar Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam sebuah acara teknologi (CNBC Indonesia, 11 November 2024). Tepuk tangan pun riuh. Koding kini dianggap bahasa masa depan—setara pentingnya dengan membaca dan menulis. Namun di antara gegap gempita itu, dua orang berdiri di pinggir taman kota tempat sebuah playdate anak usia dini berlangsung: seorang instruktur perempuan berambut pirang yang tampak samar di balik hijabnya yang sedikit miring, dan seorang pria paruh baya berwajah manis (nyaris seperti perempuan hasil kegagalan operasi plastik) tapi dikenal idealis dan cukup beringas di gelanggang beladiri.
“Lihat,” kata sang instruktur sambil menunjuk salah satu anak yang memamerkan smartwatch barunya. “Dia bilang jamnya bisa tahu detak jantungnya bahkan saat tidur.”
Pria itu tersenyum tipis. “Teknologi memang makin hebat,” ujarnya.
“Hebat, ya,” sahut sang perempuan dengan mata berbinar.
“Iya,” jawabnya tenang, “tapi pernahkah kita bertanya… apakah kita masih mengenali tubuh kita sendiri, atau justru jam itu kini mengenali kita lebih baik?”
Percakapan ringan itu menggantung di udara, seperti embun sore yang menunggu jatuh. Anak-anak terus berlari di antara konus warna-warni, sementara jam di pergelangan tangan sang instruktur bergetar pelan, memberi tahu bahwa langkahnya hari ini sudah mencapai target. Dunia terasa sibuk menghitung setiap detak, setiap langkah, setiap kalori. Semua seperti lomba tak berujung—bukan siapa paling sehat, tapi siapa paling banyak datanya.
Ia menatap jamnya dan terkekeh kecil. “Kadang aku pikir, jam ini lebih tahu hidupku daripada aku sendiri.”
Pria itu menatapnya sejenak, lalu menimpali, “Itu bukan hal baru. Di dunia olahraga, data sudah lama jadi bahasa tubuh yang baru. Tapi di dunia anak-anak, tubuh masih seharusnya jadi bahasa pertama mereka.”
Perempuan itu diam. Ia tahu benar maksudnya. Sebagai instruktur playdate, ia sering melihat anak-anak lebih sibuk menatap layar tablet ketimbang menatap satu sama lain. Dan di sela keramaian hari itu, ia kembali teringat: anak-anak kini banyak belajar dari layar, bukan dari tanah, udara, dan peluh.
Sebagai peneliti literasi fisik anak usia 3–5 tahun, pria itu pernah meneliti ratusan subjek dari berbagai latar sosial. Ia mengisap udara pelan sebelum berkata, “Laporan Kemenkes 2023 menunjukkan, rata-rata anak Indonesia menghabiskan lebih dari empat jam per hari di depan layar. Ironisnya, anak dari keluarga biasa justru lebih tinggi paparannya daripada keluarga berada.”
“Kenapa bisa begitu?” tanya sang perempuan sambil melipat tangan.
“Karena gadget sering jadi pengasuh alternatif,” jawabnya. “Di rumah yang sempit dan hidup yang terburu-buru, layar jadi taman yang murah.”
Ia tertawa pahit, lalu menambahkan, “Anak-anak memang belajar dari layar, tapi yang paling cepat mereka pelajari adalah cara duduk diam.”
Sang perempuan menunduk, menambah manis wajahnya dengan hidung mancung warisan kakek buyutnya. Anak-anak yang semestinya belajar dengan melompat dan menari kini belajar dari kursi. Tubuh mereka menjadi penonton, bukan pelaku. Ia teringat kata-kata John Dewey yang dulu dibacanya di kampus: belajar bukan hasil dari melihat, melainkan dari melakukan. Dan ia merasa, dunia kini kebalikannya.
Pria itu melanjutkan dengan nada seperti merenung, “Su, Yang, dan Li (2023) pernah bilang, kurikulum koding di PAUD akan berhasil hanya jika berbasis permainan jasmani dan sosial. Anak-anak belajar logika justru dari tubuhnya sendiri.”
“Seperti main peran ‘robot dan navigator’ itu, ya?” potong sang perempuan.
“Ya, seperti itu,” jawabnya. “Dan Akiba (2022) menambahkan: seimbanglah antara aktivitas nyata dan digital, dan satu lagi. jangan sampai yang satu menelan yang lain.”
Ia mengangguk pelan. “Berarti teknologi terbaik bukan yang membuat mereka duduk lebih lama,” katanya lirih, “tapi yang membuat mereka bergerak lebih banyak.”
“Betul,” katanya mantap. “Kalau di dunia olahraga, sensor dipakai untuk memahami tubuh, maka di dunia anak, permainanlah sensor alami pikiran mereka.”
Keduanya terdiam sejenak, menatap matahari yang mulai condong. Di kejauhan, anak-anak masih berlari dengan riang, sementara suara notifikasi dari ponsel para orang tua bersahut-sahutan seperti metronom zaman.
“Jadi, kita menolak AI di PAUD?” tanya sang perempuan setengah bercanda.
“Tidak,” jawab pria itu tenang. “Kita hanya perlu mengembalikannya ke tempatnya: alat bantu berpikir, bukan pengganti berpikir.”
Ia lalu berbicara panjang tentang Freire (1970) dan konsep pendidikan yang membangunkan kesadaran, bukan menanamkan data. Tentang Bers (2019) yang menyebut coding as a playground, tempat anak bermain sekaligus belajar logika, kreativitas, dan moralitas. Tentang guru yang seharusnya bukan sekadar instruktur, melainkan penuntun makna.
Sang perempuan mendengarkan dengan tenang, sedikit kagum pada idealisme lelaki itu yang kadang terasa seperti khotbah, tapi juga menenangkan. “Kau tahu,” katanya kemudian, “aku suka bagian ketika kau bicara soal etika di balik algoritma. Kadang aku juga merasa, setiap sistem memang punya nilai, hanya saja kita jarang diajak menanyakannya.”
Pria itu menatapnya, lalu berkata pelan, “Karena kita lebih sibuk menatap layar daripada menatap wajah.”
Langit mulai jingga. Anak-anak dipanggil satu per satu oleh orang tuanya, tawa mereka menyusut seperti gema yang perlahan habis. Perempuan itu duduk di bangku kayu, membuka jam pintarnya, dan menatap angka-angka yang terus bergerak. “Lucu ya,” ujarnya pelan, “jam ini tahu kapan aku harus berdiri, tapi tidak tahu kapan aku perlu berhenti bekerja.”
Pria itu menatapnya dengan senyum samar, seolah ingin menutup hari itu dengan satu kalimat yang sederhana tapi menggigit. “Itulah sebabnya kita masih butuh guru,” katanya, “bukan algoritma. Jam bisa menghitung detak jantung, tapi tidak bisa mengajarkan hati nurani.”
Perempuan itu tertawa kecil, memperbaiki hijabnya yang mulai miring, dan menatap anak-anak yang masih berlarian di tepi lapangan. “Selama mereka masih berlari,” katanya pelan, “mungkin dunia belum kehilangan arah.”
Dan pria itu menjawab, kali ini tanpa idealisme berlebihan, hanya dengan senyum tenang: “Ya. Karena pada akhirnya, alat boleh canggih, tapi hati dan gerak manusialah yang menentukan arah permainan.”
OUR ADDRESS
Perum Pondok Bestari Indah, Blk. B1 No.49B, Dusun Klandungan, Landungsari, Kec. Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65151
CONTACT US
WORKING HOURS
Monday - Friday
9:00 - 18:00