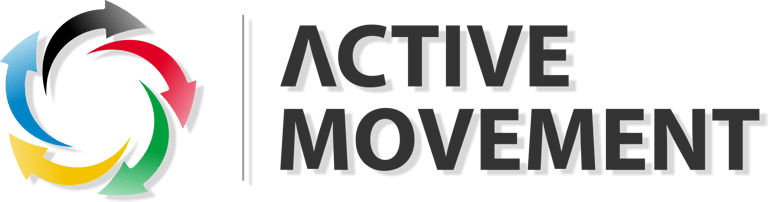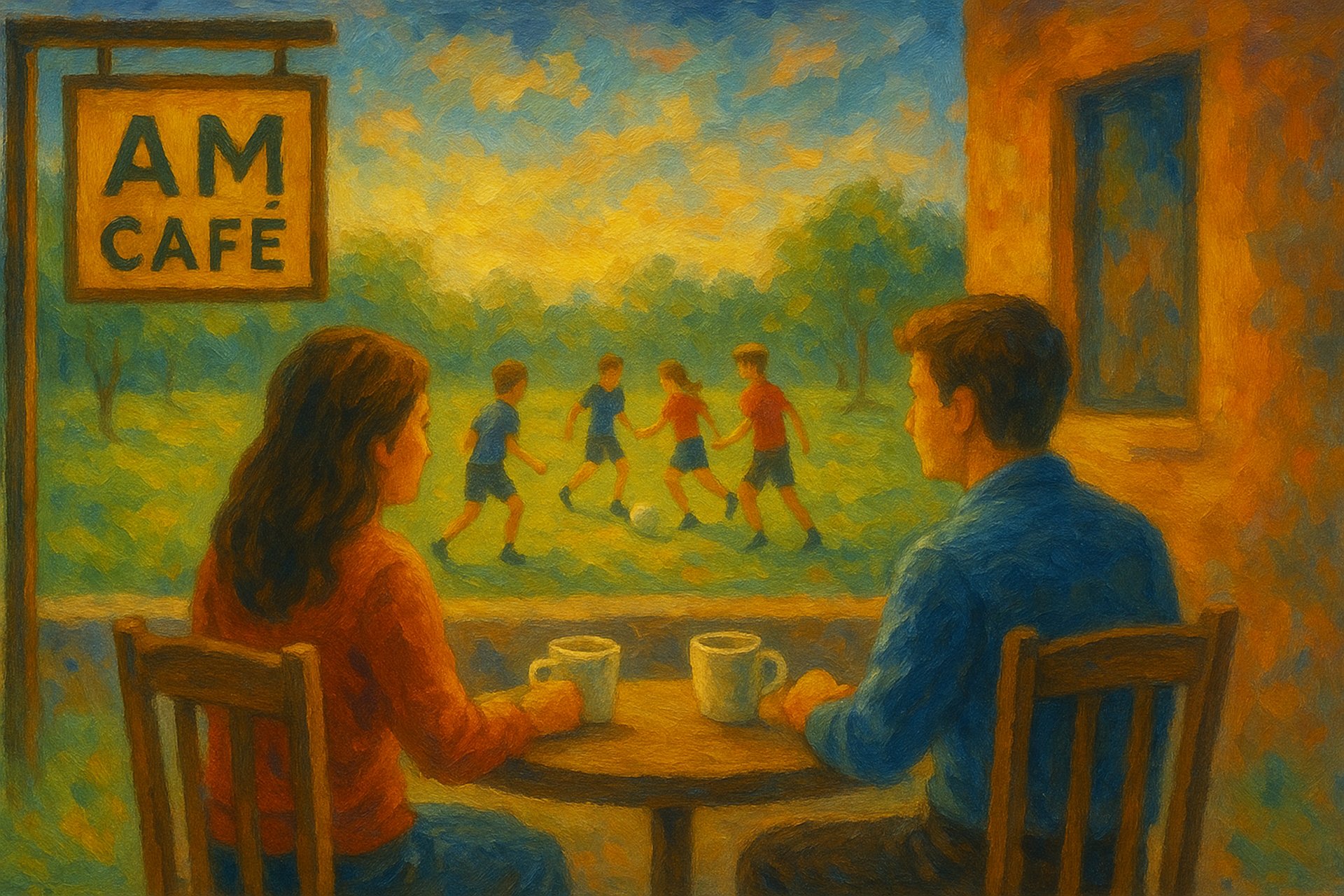
CAFE, KAPITALISME DAN MASA DEPAN OLAHRAGA ANAK
ESAI NARATIF
N.R. Fadhli
10/8/20253 min read
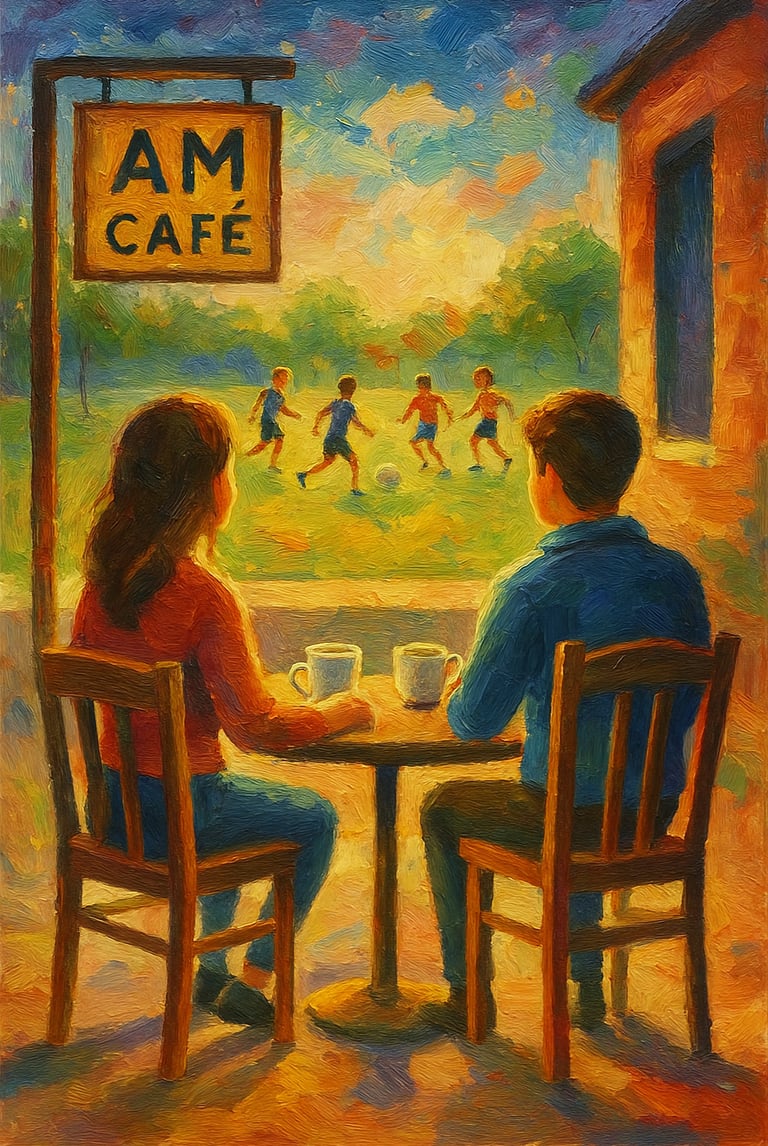
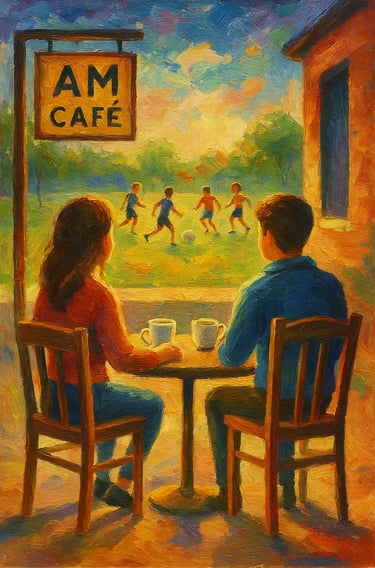
Baca Juga Lainnya: Artikel
Sore itu, cafe mewah di sudut kota menjadi tempat saya dan seorang teman lama bertemu. Lampu gantung berkilau, alunan musik jazz pelan, dan aroma kopi premium seolah menjadikan tempat ini simbol gaya hidup kalangan berada. Dari balik kaca besar, mobil-mobil mewah berderet di parkiran. Tempat ini terasa asing bagi mereka yang setiap harinya berjuang untuk tetap bisa merasakan amilosa dan amilopektin terasa manis saat makan malam.
Saya seorang pengajar di departemen pendidikan olahraga. Selama ini, saya dikenal lumayan idealis di kampus: selalu menekankan pentingnya kesetaraan akses olahraga, selalu bicara tentang hak anak untuk bermain, selalu mengkritik bagaimana pendidikan sering terjebak pada logika kapitalisme. Tapi ironi itu kini hadir di depan mata saya sendiri—klub olahraga yang saya kelola untuk anak-anak pun nyatanya hanya bisa bertahan kalau menyasar anak dari keluarga berada.
Illustrasi: Active Movement Indonesia
Teman saya, dari kota seberang pulau merupakan seorang pengusaha yang sukses mengelola pusat bimbingan anak usia dini, tersenyum sambil menyeruput cappuccino. “Bagaimana kabar klub olahragamu?” tanyanya ringan, sambil tersenyum manja.
“Jalan,” jawab saya. “Tapi jujur, dilematis sekali. Semua peserta anak orang kaya. Kadang aku merasa seperti mengkhianati prinsip yang selama ini kupegang. Aku ingin olahraga jadi ruang inklusif untuk semua anak, tapi kalau tidak menyasar orang yang punya uang, klubku tidak bisa jalan.”
Ia mengangguk pelan. “Aku paham. Pusat bimbingan anakku juga begitu. Dari awal niatku inklusif, ingin menjangkau semua kalangan. Tapi akhirnya, yang bisa bayar program mahal ya hanya kalangan menengah ke atas. Sementara anak-anak dari keluarga sederhana, yang justru lebih butuh dukungan, malah tidak bisa masuk.”
Saya menatap kopi yang mengepul di depan saya. Ada rasa getir. “Kadang aku merasa bersalah. Aku ini orang yang sejak dulu idealis, percaya bahwa olahraga itu hak sosial, bukan komoditas. Tapi roda organisasi memaksaku tunduk pada kapitalisasi. Pelatih harus digaji, lapangan harus disewa, perlengkapan harus dibeli. Semua butuh uang. Dan uang itu adanya di tangan keluarga berada.”
Teman saya menatap serius. “Bukankah itu kenyataan yang tak bisa kita elakkan? Kalau gratis, lembagamu ambruk. Kalau ikut logika pasar, ia bisa bertahan.”
Saya teringat pada kata-kata Paulo Freire: “Education either functions as an instrument to bring conformity to the system, or it becomes the practice of freedom.” Saya mengulang kalimat itu perlahan. “Aku takut klubku justru sedang berada di jalur pertama: alat yang melanggengkan sistem kapitalistik, bukan ruang pembebasan.”
Saya menghela napas panjang. “Aku tahu. Ilmuku bilang anak usia dini seharusnya bermain, eksplorasi, bergerak bebas."
Tapi orang tua peserta klub menuntut hal lain. Mereka bayar mahal, lalu datang padaku sambil bilang, "Pak, tolong latih anak saya serius ya, siapa tahu bisa jadi atlet profesional, event besok harus podium." Anaknya baru empat tahun!
Mereka menganggap olahraga bukan ruang tumbuh, tapi investasi masa depan. Aku tahu itu salah, tapi aku tak berdaya menolak, karena kalau aku terlalu idealis, klub bisa ditinggalkan. Kalau klub ditinggalkan, pelatihku kehilangan pekerjaan. Dan semua berhenti.
Saya berhenti sebentar, menatap keluar jendela. Anak-anak kecil berlarian di taman, sebagian diantar babysitter dengan seragam penuh dengan aroma kekangan, sebagian lagi mengenakan seragam kursus privat. Mereka tampak riang, tapi saya bertanya dalam hati: kegembiraan itu milik mereka, atau hanya hasil rekayasa pasar orang dewasa?
Dengan suara lirih saya menambahkan, “Ivan Illich pernah menulis dalam *Deschooling Society ‘The pupil is schooled to confuse teaching with learning, diploma with competence, fluency with the ability to say something new.’ Bukankah sekarang kita sedang membuat anak-anak mengira olahraga itu soal sertifikat, medali, fasilitas mahal—bukan tentang kebebasan bergerak?”
Teman saya mengangguk. “Jadi intinya kamu masih idealis, tapi terjebak dalam sistem, atau bagaimana?”
Saya tersenyum pahit. “Benar. Aku idealis, aku percaya olahraga seharusnya milik semua. Tapi keadaan memaksaku menciptakan sistem yang kapitalis. Dan di situlah dilema paling besar dalam hidupku.”
Kami pun terdiam. Musik jazz café terus mengalun, kopi semakin dingin. Di ruang mewah itu, saya merasa sesak. Semua prinsip sosial yang dulu saya perjuangkan kini beradu keras dengan realitas. Dan mungkin, inilah yang paling menyakitkan: menyadari bahwa idealisme bisa bertahan di kelas, di tulisan, di seminar. Tapi di dunia nyata, ia seringkali harus tunduk pada pasar.
Saya berdiri, bersiap pergi. Café mewah ini terlalu pas untuk jadi simbol. Indah, hangat, nyaman, tapi jelas bukan untuk semua. Sama seperti klub olahraga yang saya kelola. Dalam hati, saya bertanya lirih: apakah suatu hari ada jalan keluar? Atau idealisme saya akan terus menjadi korban kapitalisasi?
OUR ADDRESS
Perum Pondok Bestari Indah, Blk. B1 No.49B, Dusun Klandungan, Landungsari, Kec. Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65151
CONTACT US
WORKING HOURS
Monday - Friday
9:00 - 18:00