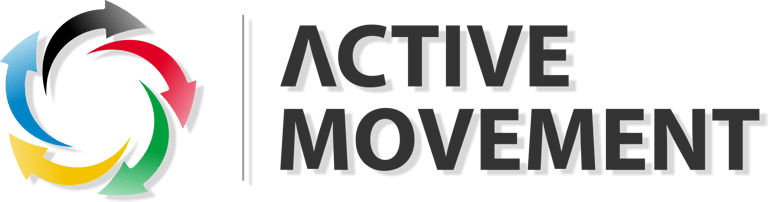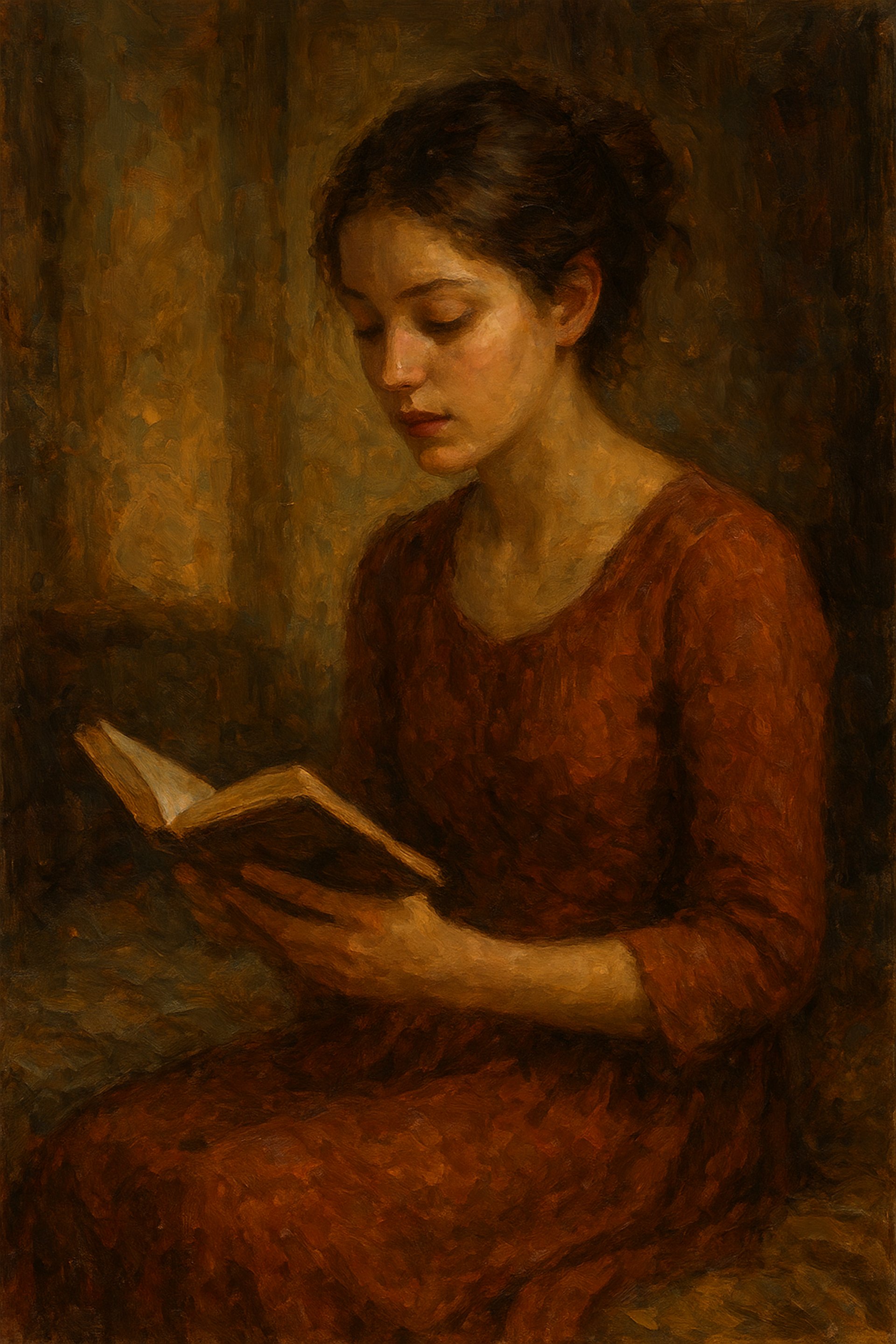
Buku Dipinjam Tidak Kembali yang Saya Syukuri, Pahlawan, dan Legenda Sepakbola
OPINI
Arif Subekti
11/25/20254 min read
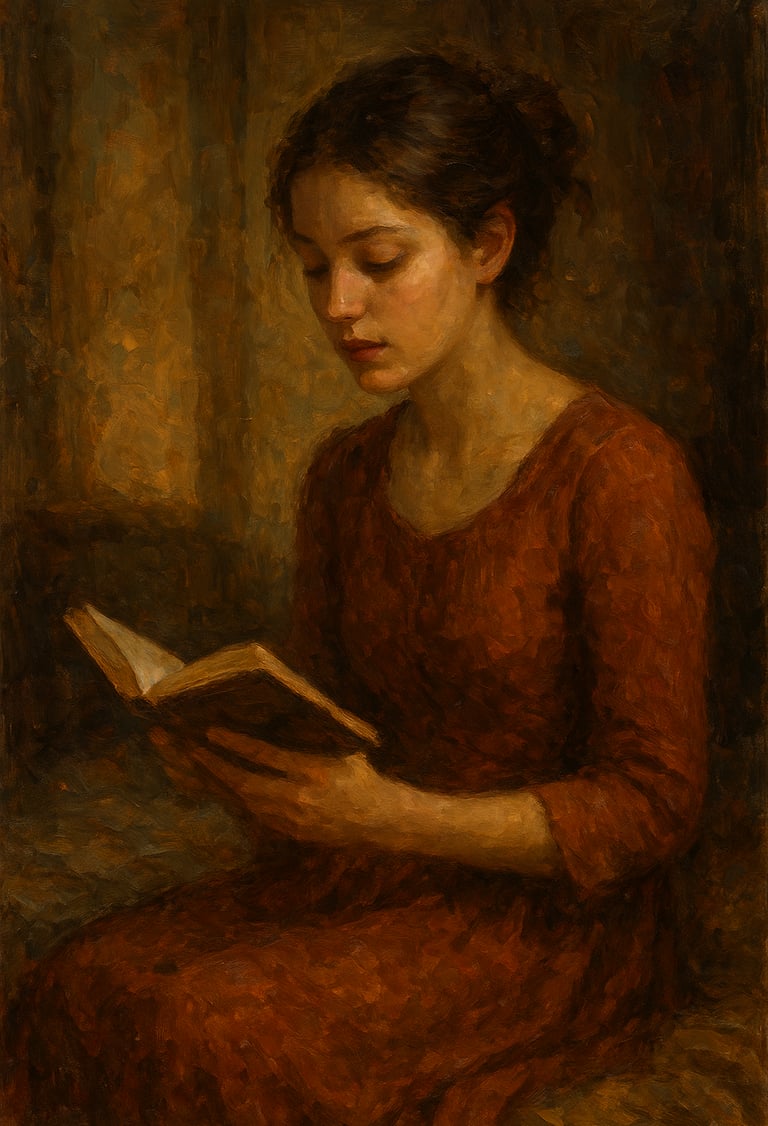
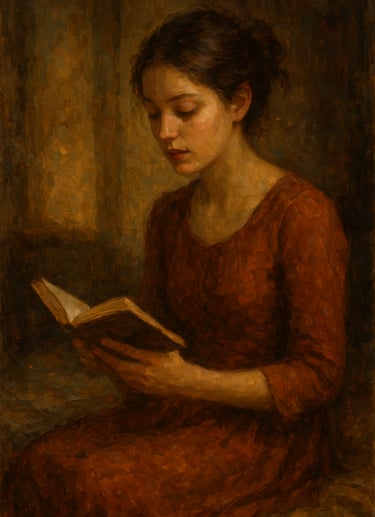
Semester gasal ini, saya mengajar matakuliah Politik Memori. Matakuliah pilihan yang di beberapa pertemuan, mahasiswa banyak saya berikan tugas melakukan wawancara. Karena tidak (belum) ada matakuliah Sejarah Lisan, maka saya meminta mahasiswa mengakses laman sejarah.lisan.fis.um.ac.id; isi dari laman website ini adalah bekal dasar sebelum seorang sejarawan (dan akademisi lainnya) melakukan penggalian sumber lisan.
Saya juga memberikan contoh karya historiografi yang terkait dengan sumber lisan, yang terkait dengan politik ingatan, seperti Tahun yang Tak Pernah Berakhir. Saya bilang ke mahasiswa, baca bagian pendahuluan dari John Roosa, “bagus banget untuk bekal kalian memahami metode sejarah lisan”. Nah, ada satu buku yang saya rekomendasikan untuk mereka baca, tapi saya tidak banyak berkomentar perihal isi bukunya. Judulnya, Suara Perempuan Korban 65.
Ilustrasi: Active Movement Indonesia
“Ini mungkin satu-satunya buku saya yang dipinjam entah siapa, dan tidak kembali, namun saya tidak menyesalinya. Saya malah bersyukur buku itu tidak ada di rak buku saya”. Saya bilang begitu ke mereka.
Mengapa? Bukan karena buku itu tidak ilmiah, sehingga menyesatkan, membentuk pseudo-history, dan sebagainya. Bukan sama sekali. Buku ini bagus banget. Ditulis oleh sejarawan yang hebat. Cuma saya saja yang tidak punya nyali, tidak tega membacanya dua kali. Cukup sepisan wae baca buku ini sampai selesai. Setelah itu, saya tidak punya nyali. Ora tegel, istilah Jawa ini, mungkin tidak tepat, tapi itu yang saya rasakan.
Mengapa ora tegel? Isinya adalah cerita tentang 8 sampai 10 perempuan yang ditemui Ita Fatia Nadia, penulisnya, yang menceritakan kekerasan yang mereka alami. Saya tidak ingin mengingat-ingat isinya, tapi saya ingin mahasiswa matakuliah Politik Memori membaca buku ini. Saya kasih spill, ada kisah nenek yang jadi tukang pijit dan penulis buku itu pasiennya. Sambil dipijit, nenek tersebut bercerita tapi kesulitan mengingat masa lalunya. Kalau tidak keliru, karena kepala nenek tersebut dihantamkan ke tembok berkali-kali waktu disiksa. Lainnya, saya ndak spill, ora tegel. Maaf, saya terlalu cengeng. Titik tekan saya, metode sejarah lisan bagi sejarawan, terkadang membuat si sejarawan menanggung beban trauma, dalam hal ini informasi kekerasan yang ia himpun. Ini barangkali mirip dengan penderitaan yang dialami Kevin Carter, fotografer peraih penghargaan Pulitzer 1994 yang bunuh diri empat bulan setelah menerima penghargaan itu. Ia menanggung trauma dan rasa bersalah karena (hanya) mengambil gambar anak kecil penderita malnutrisi di masa kelaparan Sudan yang tengah diincar burung bangkai, dimana gambar itulah yang menjadikannya peraih Pulitzer.
Saya suka nonton bola, fans AC Milan, Liverpool, dan PSIS Semarang. Sejak SD, Bapak entah sengaja atau tidak, mengenalkan saya dengan olahraga ini. Saya ingat, kami nonton bola di RCTI, waktu Filippo Inzaghi masih di Juventus, bibrnya berdarah karena benturan. Saya tidak tega melihat pesepakbola ganteng itu bercucuran darah. Seingat saya, bibirnya dipasangi sesuatu seperti wadah janggutnya helm batok, tapi berwarna bening.
Saya juga tidak tega, melihat proses alis Jaap Stam dijahit dan tidak disensor waktu Euro 2000. Atau waktu tangan Carles Puyol dislokasi karena salah jatuh, waktu Barca main di Champions; kaki Djibril Cisse yang patah waktu jadi ujung tombak Liverpool; atau yang paling anyar, engkel Musiala waktu lawan PSG. Nggegirisi.
Mungkin seperti itulah kecengengan saya menghadapi buku Bu Ita di atas. Buku sejarah perempuan lain, seperti Nyai dan Pergundikannya Reggie Baay; Barracks Concubinage-nya Hanneke Ming, masih oke lah. Agak melo dan sensitif ketika tugas matakuliah Sejarah dan Politik Memori waktu saya kuliah di Jogja adalah mereview buku Penghancuran Gerakan Perempuan. Komentar dosen pengampunya, saya tidak mereview buku itu secara ilmiah, tapi malah memaparkan belas kasihan kepada satu pihak, dan menyampaikan hujatan kebencian kepada pihak lain.
Saya tidak tahu, apakah permainan kasar satu tim sepakbola yang direncanakan oleh pelatih sebagai bagian dari taktik, hukumannya juga dijatuhkan kepada pelatihnya selain kepada pemain yang melakukan pelanggaran keras tersebut.
Misal, pemain FC Aspal Goreng ditugaskan oleh pelatihnya untuk mencederai pemain FC Tikitaka, sehingga beberapa pemainnya terkena cedera parah, bahkan ada satu dua yang harus gantung sepatu. Nah, karena terbukti pelatihnya menyusun rencana jahat ini, pemainnya terbukti sengaja melakukan pelanggaran keras menjurus pada tindak pidana, maka komdis Liga Byalbalan Jaya menjatuhkan hukuman. Si pelatih dilarang lagi melatih, menonton bola, jadi pundit, mendirikan SSB, dan segala hal yang berkaitan dengan sepak bola. Kalaupun tidak dihukum dan masih boleh berkecimpung di dunia sepak bola, setidak-tidaknya, si pelatih dicap tidak menjunjung prinsip fair play sepanjang hidupnya. Juga setelah kematiannya, ia dikenang sebagai pelatih yang tidak pantas dicontoh oleh generasi penerus sepak bola. Alih-alih, mematungkannya di depan stadion, menulis biografi dan membedahnya di kafe cozy, serta mengenangnya sebagai legenda sepak bola.
Mengapa? Karena jika si pelatih diangkat sebagai legenda sepak bola, seluruh anggota klub FC Tikitaka khususnya korban tekel brutal juga sanak keluarganya, anak turunnya akan memendam kekecewaan yang mendalam. Para pemain yang harus gantung sepatu karena permainan kasar anak buah si pelatih FC Aspal Goreng akan ngerantes seumur hidup. Bahwa komisi sepakbola Liga Byalbalan Jaya telah melakukan tindakan tidak adil, tidak menjunjung nilai luhur fair play, bahkan nilai-nilai kemanusiaan.
Kembali ke topik sejarah. Agus Mulyadi alias Agus Magelangan, baru-baru ini memosting video pendek (tapi agak panjang) di laman sosial medianya, perihal nalar sehat dan pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan. Ia mengatakan membagi pihak pro dan kontra terkait pengangkatan Soeharto.
“Bagi orang-orang yang mendukung pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan, merasa hidup enak di masa Soeharto, gelar pahlawan itu tidak akan menimbulkan dampak apa-apa bagi hidupnya. Tetapi sebaliknya, bagi orang yang kontra, yang menderita kekerasan HAM di masa rezim Soeharto, pemberian gelar pahlawan itu menihilkan rasa sakit mereka. Dan makin memperbesar luka atas ketidakadilan yang sudah mereka dapatkan di masa lalu. Mereka menyimpan lukanya seumur hidup. Selamanya..”
Di akhir video, Agus Mulyadi menutup narasi dengan menegaskan bahwa menolak pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto adalah sikap dasar, bukan hanya oleh para korban kekejaman rezim Orba, tapi bahkan bagi orang yang merasa hidup enak di masa Orde Baru. Kalaupun hati merasa tidak cocok untuk menolak, minimal diam saja, tidak usah ikutan mendukung. Kalau Anda orang awam biasa—bukan politikus atau orang yang diuntungkan secara politik-ekonomi dalam polemik gelar pahlawan bagi Soeharto ini alias tidak mendapatkan keuntungan apa-apa—tapi ngotot mendukung keputusan pemberian gelar pahlawan ini, padahal menyakiti korban dari rezim Orba, maka kemungkinanya ada tiga: pertama, Anda bukan orang yang bijak; kedua, Anda orang yang bodoh, dan ketiga, Anda orang jahat.
Uniknya, beberapa tokoh nasional seperti Gus Mus menegaskan bahwa orang (NU) yang mendukung Soeharto jadi pahlawan adalah orang yang tidak mengerti sejarah. Mungkin maksudnya adalah, karena sejarah mengajarkan kebijaksanaan, maka orang (NU) yang mendukung pengusulan dan penetapan Soeharto jadi pahlawan adalah orang yang tidak bijak, karena tidak membaca dan mengerti sejarah.
Sekarang, mari kita bayangkan. Jika seorang pernah atau sedang menjadi mahasiswa di Jurusan Sejarah, atau sudah lulus dari jurusan ini kemudian kersane Gusti Allah, jadi guru sejarah, atau syukur Alhamdulillah sampai jadi dosen sejarah, namun cilakanya mendukung Soeharto sebagai pahlawan. Alhasil, jika orang (mahasiswa sejarah, guru sejarah, dosen sejarah, sejarawan) itu masuk kategori Agus Mulaydi sebagai tidak bijak, maka ketidakbijaksanaannya mungkin kuadrat. Pun jika orang itu (mahasiswa sejarah, guru sejarah, dosen sejarah, sejarawan) bodoh, maka bodohnya kuadrat. Saya tidak membayangkan yang ketiga, jahat kuadrat.
OUR ADDRESS
Perum Pondok Bestari Indah, Blk. B1 No.49B, Dusun Klandungan, Landungsari, Kec. Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65151
CONTACT US
WORKING HOURS
Monday - Friday
9:00 - 18:00