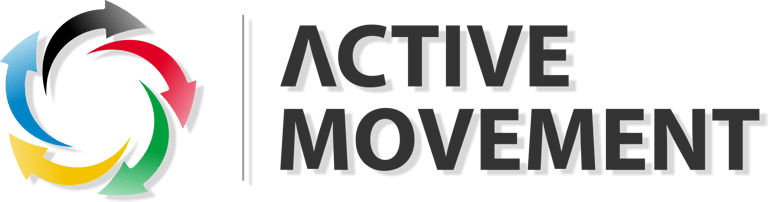Bermain di Bawah Pengawasan: Potret Baru Masa Kanak-Kanak Urban
ULASAN
N.R. Fadhli
10/14/20256 min read

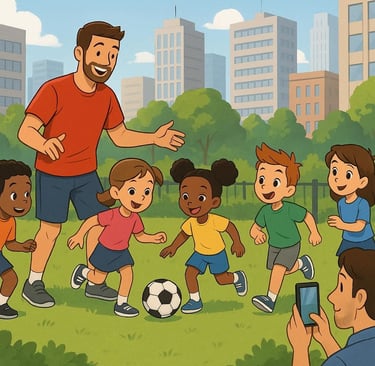
Ilustrasi: Active Movement Indonesia
Di sebuah sore yang gerimis di Malang, suara anak-anak di taman Kota terdengar sayup, teredam oleh deru kendaraan. Taman yang tidak sepenuhnya sehat, karena berada diantara per-8 simpangana jalan. Seorang ibu muda duduk di bangku beton sambil menatap layar ponselnya, bukan untuk bersantai, melainkan memastikan jadwal play date anaknya akhir pekan ini. “Supaya nggak ketinggalan main sama teman-teman sekolah,” katanya pelan pada dirinya sendiri. Tapi di balik kalimat sederhana itu, tersimpan sesuatu yang jauh lebih kompleks, tentang kelas sosial, harapan orang tua, dan perubahan wajah masa kanak-kanak di dunia modern.
Fenomena inilah yang menjadi denyut utama dalam artikel ilmiah karya Alison J. Lacey, Robin A. Banerjee, dan Kathryn J. Lester (2023) berjudul “Are They Going to Play Nicely? Parents’ Evaluations of Young Children’s Play Dates”, diterbitkan di Journal of Child and Family Studies (https://doi.org/10.1007/s10826-022-02499-4). Dengan pendekatan kualitatif yang lembut namun tajam, penelitian ini membedah dunia kecil tapi sarat makna: pertemuan bermain anak-anak usia 5–6 tahun di Inggris, yang tampaknya sederhana, namun ternyata menjadi ruang sosial yang dikontrol, diatur, dan dipolitisasi oleh orang tua.
Di permukaan, play date tampak seperti ajang anak-anak bermain lego, menggambar, atau berlari di halaman belakang. Namun dalam wawancara mendalam terhadap sebelas orang tua, para peneliti menemukan bahwa di balik tawa dan kue cokelat yang disajikan, terselip dinamika sosial yang meniru dunia orang dewasa: status, jaringan, dan eksklusi. Play date bukan lagi permainan spontan anak-anak, tetapi menjadi “miniatur masyarakat kecil”, di mana orang tua berperan sebagai kurator sosial bagi anak-anak mereka.
Para peneliti mencatat bahwa kesempatan anak untuk bermain bebas di luar rumah telah menurun drastis dalam dua dekade terakhir (Baines & Blatchford, 2019). Ketakutan akan keamanan, urbanisasi, serta tekanan akademik membuat anak-anak jarang bermain spontan di jalan atau lapangan. Akibatnya, play date menjadi satu-satunya bentuk permainan sosial yang tersisa. Tapi ironisnya, ruang yang seharusnya bebas itu kini justru dikontrol dengan sangat ketat. Orang tua menentukan siapa yang boleh datang, berapa lama, bahkan jenis permainan apa yang dianggap “layak.”
Dalam wawancara, banyak orang tua menggambarkan play date sebagai pertemuan yang “terstruktur namun menyenangkan.” Mereka menyiapkan makanan, mengawasi dari kejauhan, dan memastikan anak-anak “bermain dengan sopan.” Tapi konsep “sopan” ini ternyata penuh muatan nilai sosial. Orang tua cenderung hanya mangajak keluarga atau teman dari mereka yang dianggap “sepadan”, dengan latar belakang, nilai, atau bahkan gaya hidup yang mirip. Salah satu ibu mengaku bahwa ia hanya mengizinkan anaknya pergi ke rumah “orang tua yang saya kenal dan nyaman.” Lacey dkk. menyebut kecenderungan ini sebagai bentuk gatekeeping sosial: orang tua menjadi penjaga pintu yang menentukan akses anak terhadap jaringan sosialnya.
Fenomena ini mengingatkan kita pada realitas yang semakin terasa di kota-kota besar Indonesia. Di perumahan menengah, taman bermain kerap sepi, tapi grup WhatsApp orang tua TK penuh dengan agenda play date di kafe ramah anak. Permainan tidak lagi lahir dari spontanitas, tetapi dari kalender dan kesepakatan sosial antar orang tua. Dalam konteks ini, play date mencerminkan perubahan cara kita memandang masa kanak-kanak, dari dunia eksplorasi menjadi proyek sosial yang harus dikawal.
Penelitian Lacey dan koleganya menunjukkan bahwa orang tua melihat play date bukan sekadar hiburan, tetapi sarana “pengembangan sosial-emosional.” Mereka percaya bahwa melalui play date, anak belajar berbagi, bernegosiasi, dan mengatur konflik. Tetapi di sisi lain, banyak orang tua mengaku cemas: apakah anaknya cukup “disukai,” apakah rumahnya tampak rapi, apakah tamu kecil itu akan “menilai” mainan yang dimiliki. Di titik ini, play date bukan lagi ruang bermain anak, melainkan cermin dari kecemasan kelas menengah tentang reputasi dan penerimaan sosial.
Situasi ini mengingatkan pada konsep intensive parenting yang dikemukakan oleh Craig dan Mullan (2010, Journal of Comparative Family Studies), yakni bentuk pengasuhan yang sangat terencana, penuh strategi, dan berorientasi prestasi. Dalam masyarakat modern, orang tua berlomba menciptakan “lingkungan terbaik” untuk anak, tetapi sering tanpa sadar, mereka justru mengekang kebebasan anak untuk tumbuh melalui pengalaman spontan.
Temuan lain yang menarik dalam artikel ini adalah perubahan peran pengawasan. Lacey dkk. menggunakan kerangka Vigilant Care Model (Omer et al., 2016), yang membedakan antara “open attention” (pengawasan longgar namun responsif) dan “active protection” (intervensi langsung). Mayoritas orang tua dalam studi ini masih kesulitan menerapkan “open attention.” Mereka tahu bahwa anak perlu kebebasan, tetapi rasa cemas membuat mereka terus memantau dari balik pintu dapur. Hasilnya, play date menjadi ruang semi-bebas: anak-anak bermain, tetapi dalam batas pandangan dan kontrol orang dewasa.
Jika kita tarik benang ke Indonesia, pola serupa muncul dalam perubahan lanskap bermain anak. Laporan UNICEF (2021) mencatat bahwa anak-anak di kota besar Indonesia mengalami penurunan drastis dalam waktu bermain bebas di luar ruangan. Alih-alih bermain petak umpet atau bersepeda di gang, mereka lebih sering berada di dalam rumah dengan gadget, atau menghadiri play date terjadwal di mal dan indoor playground. Seperti di Inggris, kesempatan bermain kini bergantung pada kemampuan ekonomi dan jaringan sosial orang tua. Anak dari keluarga dengan akses terbatas kehilangan kesempatan bersosialisasi, bukan karena tidak mau bermain, tetapi karena tidak punya “undangan.”
Dalam arti tertentu, play date menciptakan stratifikasi sosial baru dalam masa kanak-kanak. Di Inggris, Lacey dkk. menemukan bahwa anak-anak dengan “status sosial” tinggi lebih sering diundang bermain; di Indonesia, fenomena serupa terjadi melalui bentuk yang berbeda, akses terhadap ekstrakurikuler premium, taman bermain berbayar, atau sekolah yang mempromosikan “lingkungan bermain positif.” Semua ini menunjukkan bagaimana permainan anak telah menjadi bagian dari proyek kapital sosial keluarga.
Namun di sisi lain, penelitian ini juga memperlihatkan sisi manusiawi yang hangat. Banyak orang tua yang jujur mengaku bahwa play date membantu mereka membangun komunitas kecil, bertukar cerita, dan saling membantu dalam pengasuhan. Ada rasa kebersamaan di tengah tekanan sosial yang tinggi. Ini membuka ruang refleksi: barangkali play date bukan sekadar simbol kontrol, tapi juga cara orang tua mencari koneksi sosial di dunia urban yang makin terisolasi.
Menariknya, temuan Lacey dkk. sejalan dengan riset-riset internasional lain yang juga terindeks Scopus. Misalnya, penelitian oleh Gray (2011) dalam American Journal of Play yang menunjukkan bahwa berkurangnya permainan bebas anak berhubungan dengan meningkatnya gangguan kecemasan dan depresi di masa kanak-kanak. Anak-anak yang selalu diawasi dan jarang memiliki otonomi dalam bermain cenderung kurang resilient, mudah cemas, dan kesulitan mengatur emosi. Temuan serupa juga muncul dalam riset Tremblay et al. (2015, Journal of Child Psychology and Psychiatry), yang menekankan pentingnya self-directed play untuk perkembangan sosial dan regulasi diri anak. Dalam konteks ini, play date yang terlalu dikontrol justru berpotensi meniadakan manfaat bermain itu sendiri.
Fenomena ini menjadi cermin bagi masyarakat Indonesia yang tengah berubah cepat. Di satu sisi, urbanisasi dan kesibukan orang tua membuat ruang bermain alami menyusut. Di sisi lain, muncul budaya baru: “Komersialisasi ruang bermain anak di Indonesia mencerminkan tren yang lebih luas dalam perkembangan perkotaan dan perubahan budaya.” Fenomena ini menunjukkan bagaimana ruang bermain beralih fungsi menjadi bagian dari strategi ekonomi dan konsumsi keluarga urban. Meski meningkatkan akses rekreasi, komersialisasi berisiko menggerus identitas budaya dan makna sosial masa kanak-kanak. Ini adalah versi lokal dari play date society yang ditemukan Lacey di Inggris, sebuah dunia di mana kebebasan anak dikemas dalam kemasan sopan dan eksklusif.
Namun, tak semuanya suram. Artikel Lacey juga memberi kita harapan: orang tua sejatinya memahami nilai permainan bebas, hanya saja mereka terjebak dalam ekspektasi sosial. Banyak di antara mereka yang berkata bahwa mereka ingin anak “pergi bermain tanpa dijadwalkan,” tapi merasa dunia kini terlalu berisiko. Maka tantangannya adalah bagaimana menciptakan ekosistem yang aman namun tetap memberi ruang kebebasan. Di sinilah pentingnya kebijakan publik dan inisiatif komunitas.
Di Indonesia, gerakan semacam Kampung Dolanan di Yogyakarta, Taman Layak Anak di Surabaya, Bobocil di Mataram atau Active Movenet Indonesia yang menghidupkan aktivitas fisik anak di ruang terbuka, adalah contoh upaya lokal yang selaras dengan semangat penelitian ini. Gerakan-gerakan ini berusaha merebut kembali ruang bermain anak dari genggaman jadwal dan layar.
Bila kita meminjam lensa yang lebih luas, artikel Lacey bukan sekadar studi tentang play date, melainkan refleksi tentang transformasi keluarga modern, bagaimana cinta dan kecemasan berjalan berdampingan. Orang tua ingin anak bahagia, tapi juga ingin mereka “terlihat” baik di mata sosial. Dalam proses itu, bermain yang merupakan aktivitas paling natural bagi anak saat ini perlahan berubah menjadi ajang representasi sosial.
Di akhir tulisannya, Lacey dkk. mengingatkan bahwa play date seharusnya menjadi jembatan antara dunia rumah dan dunia teman sebaya, bukan dinding eksklusif. Mereka mengajak peneliti masa depan untuk menelaah bagaimana peran pengawasan orang tua memoderasi kualitas permainan, serta bagaimana ketimpangan akses dapat memengaruhi perkembangan sosial anak. Di Indonesia, pesan ini terasa mendesak. Saat kesenjangan sosial meningkat dan ruang publik menyempit, anak-anak yang miskin akses bermain berisiko kehilangan kesempatan membangun empati, kerja sama, dan keceriaan spontan yang menjadi fondasi kemanusiaan.
Bermain, seperti yang dikatakan ahli perkembangan anak Peter Gray, adalah “sekolah pertama untuk demokrasi.” Dalam permainan bebas, anak belajar aturan, negosiasi, bahkan konflik tanpa instruksi. Jika ruang itu tertutup oleh pagar sosial, maka kita sedang kehilangan sesuatu yang sangat berharga: kebebasan anak untuk menjadi dirinya sendiri.
Dan mungkin, di sore gerimis di Malang itu, ketika ibu muda tadi menatap layar ponselnya, yang sebenarnya ia cari bukan hanya jadwal play date anaknya, tapi juga cara untuk merasa tenang di dunia yang makin penuh kecemasan. Dunia tempat anak-anak bermain dengan “baik,” tapi barangkali tak lagi benar-benar bebas.
Referensi Relevan
Lacey, A. J., Banerjee, R. A., & Lester, K. J. (2023). Are They Going to Play Nicely? Parents’ Evaluations of Young Children’s Play Dates. Journal of Child and Family Studies, 32, 2240–2253. https://doi.org/10.1007/s10826-022-02499-4
Gray, P. (2011). The Decline of Play and the Rise of Psychopathology in Children and Adolescents. American Journal of Play, 3(4), 443–463.
Tremblay, M. S., Gray, C., Babcock, S., et al. (2015). Position Statement on Active Outdoor Play. International Journal of Environmental Research and Public Health, 12(6), 6475–6505. https://doi.org/10.3390/ijerph120606475
Craig, L., & Mullan, K. (2010). Parenthood, Gender and Work–Family Time in the United States, Australia, Italy, France, and Denmark. Journal of Comparative Family Studies, 41(4), 637–660.
Suharsono, T., & Putri, R. E. (2022). Komodifikasi Masa Kanak-kanak dalam Ruang Bermain Komersial di Perkotaan Indonesia. Jurnal Sosiologi Pendidikan Indonesia, 6(2), 115–132.
OUR ADDRESS
Perum Pondok Bestari Indah, Blk. B1 No.49B, Dusun Klandungan, Landungsari, Kec. Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65151
CONTACT US
WORKING HOURS
Monday - Friday
9:00 - 18:00